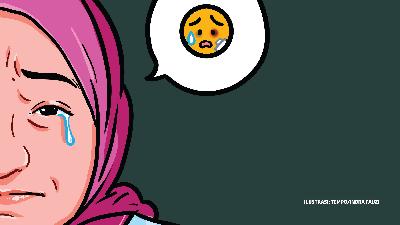Dilema Masyarakat Adat dalam Pilkada
Masyarakat adat menggunakan agenda politik untuk memperjuangan hak mereka. Kerap dilemahkan praktik kotor politik praktis.
arsip tempo : 173074414634.
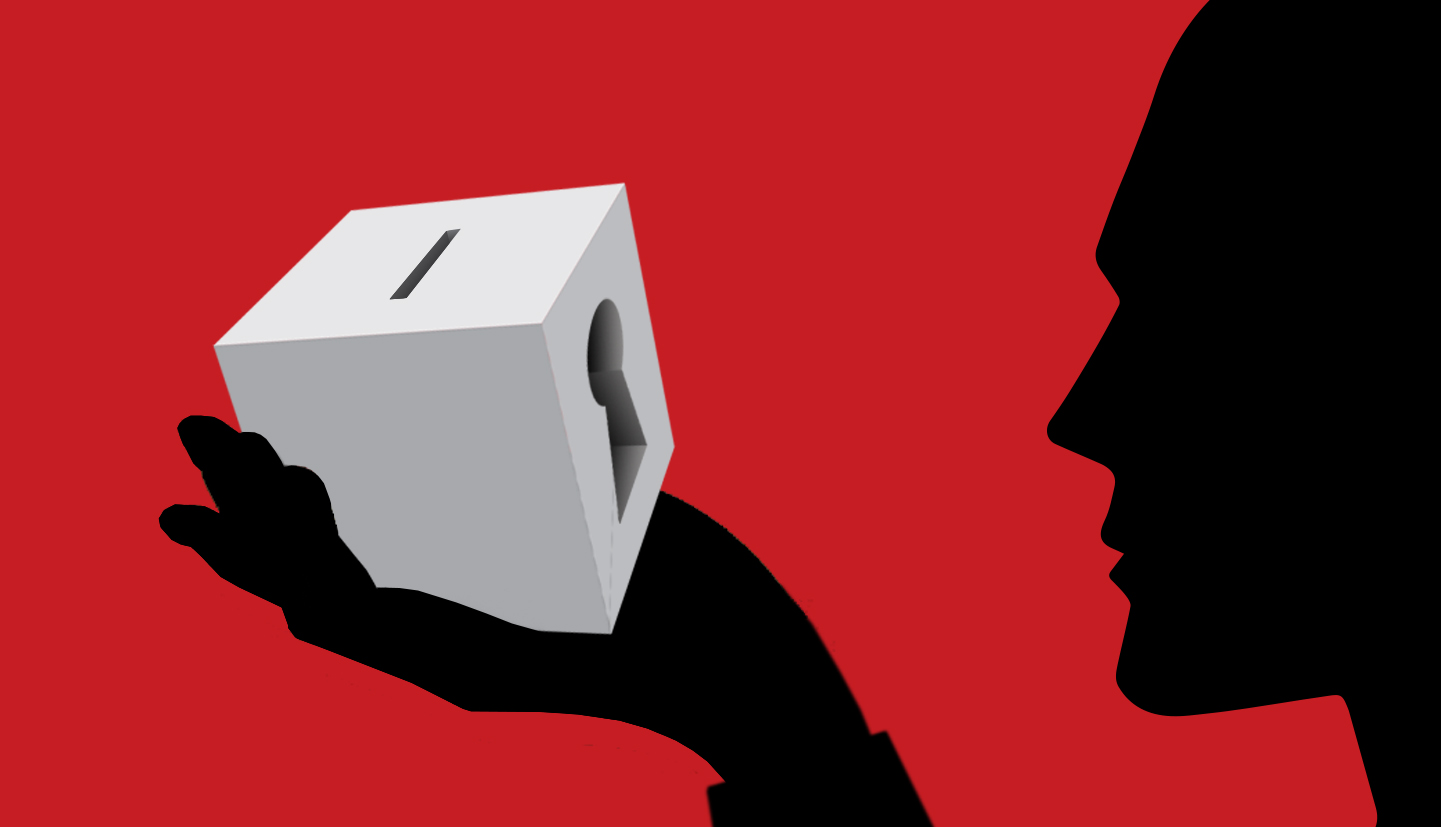
INGAR-bingar pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak 2024 telah bergulir. Data Komisi Pemilihan Umum menunjukkan pilkada serentak kali ini akan dilaksanakan di 37 provinsi dan 308 kabupaten/kota.
Pilkada memang derivasi dari veto reformasi melalui adanya desentralisasi. Tapi banyak pakar menyebutkan desentralisasi melalui otonomi daerah ataupun otonomi khusus di beberapa daerah sebenarnya tak menghadirkan perubahan radikal.
Dengan demikian, jangan terlalu heran kalau pembukaan keran pemilihan kepala daerah di tingkat lokal malah memunculkan politik uang, kartel, oligarki, sosok orang kuat lokal atau local strong men, dan sebagainya. Penyakit inilah yang menjadi langgam pilkada selama ini.
Kalaupun ada sesuatu yang baru, bisa saja bentuknya berupa politik gerakan sosial. Suatu napas baru dalam dinamika politik lokal—berkat adanya kekuatan politik kewargaan—yang bertumpu pada komunitas-komunitas dengan warna perjuangan masing-masing.
Salah satu gerakan politik kewargaan yang sangat intens terlibat dalam politik elektoral adalah Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN). Semangat politik keterlibatan dari AMAN selama ini sudah dikumandangkan sejak dua dekade lalu.
Agenda politik AMAN dapat disebut terstruktur. Sebab, menghubungkan beberapa elemen politik, seperti kekuatan massa di komunitas; kerja-kerja advokasi, baik litigasi maupun nonlitigasi; hingga mengutus kader dalam pentas politik elektoral (Teredi, 2021).
Politik Adat dan HAM
Namun gerakan politik yang dijalankan masyarakat adat masih menimbulkan semacam sikap sinisme terhadap publik. Hal ini muncul karena, dalam sejarahnya, kosakata masyarakat adat dalam politik elektoral identik dengan komoditas elite, didisiplinkan oleh kekuasaan, dan semacamnya.
Tapi, jauh sebelum itu, perlu dipertegas bahwa gerakan politik AMAN berpijak pada napas gerakan hak asasi manusia. Untuk memahami itu, dua pertanyaan penting harus diajukan ihwal siapakah masyarakat adat itu dan apa saja hak-hak mereka?
Genealogi HAM memang tidak terlepas dari ragam perdebatan. Karena itu, para pakar HAM di dunia dengan jujur mengatakan HAM bukanlah suatu konsep yang turun dari surga—dalam arti kebenarannya bersifat totalitas dan final. Konsep HAM selalu bersifat dialektis sampai kapan pun.
Pada generasi awal, gerakan HAM sangat kental akan tradisi liberalisme yang menekan pada hak individual. Hanna Arent mengkritik dominasi liberalisme tersebut. Arendt justru mengajukan HAM harus mampu mengakomodasi hak-hak manusia yang hidup dalam satu komunitas (Hardiman, 2009).
Dialektika perdebatan HAM pun berlanjut. Sampai salah satu pakar di bidang ini, Prof Anaya, mengajukan suatu gugatan konseptual untuk menjawab pertanyaan pertama mengenai siapa itu masyarakat adat.
Menurut Anaya, makna masyarakat adat atau indigenous peoples mengandung dua makna. Pertama, indigenous karena akar turun-temurun kehidupan mereka menjadi satu kesatuan tak terpisahkan dengan tanah dan wilayah di mana mereka huni atau akan huni.
Kedua, mereka juga disebut peoples dalam arti mereka merupakan komunitas yang unik dengan eksistensi dan identitas mereka yang berkelanjutan secara turun-temurun, yang menghubungkan mereka dengan komunitas, suku, atau bangsa dari sejarah masa lampaunya (Riyadi, 2002)
Rakitan dan racikan ragam konsep tersebut diterjemahkan dalam Pasal 25 United Nations Draft Declaration on the Rights of Indigenous Peoples (UNDRIP). Bunyinya: “Masyarakat adat memiliki hak untuk mempertahankan dan mengembangkan hubungan khas mereka, baik secara spiritual maupun material, dengan tanah, teritori, air dan wilayah-wilayah lepas pantai, serta sumber-sumber lainnya yang secara tradisional atau turun-temurun telah mereka miliki, atau bisa juga yang telah mereka duduki atau gunakan selama jangka waktu yang sudah lama sekali, dan meningkatkan tanggung jawab mereka akan nasib generasi masa depan.”
Jadi bisa dikatakan gerakan politik masyarakat adat tidak terlepas dari napas perjuangan mengenai HAM bagi masyarakat adat sendiri. Sebab, untuk mempertahankan hak-hak yang bersifat bawaan, mereka butuh perjuangan politik elektoral dengan misi menghadirkan kebijakan lokal yang akomodatif dengan kehidupan masyarakat adat sesuai dengan napas HAM.
Ragam Dilema dan Siasatnya
Sekalipun napas HAM menjadi dasar gerakan masyarakat adat, ragam dilema dan hambatan dalam politik lokal yang dihadapi juga begitu banyak. Penulis memetakan sebagian kecil ragam dilema dan hambatan itu, baik yang berdimensi internal maupun eksternal.
Pertama, politik elektoral di tingkat lokal tetap akan berjalan seperti biasanya, yakni menguatnya politik oligarki (Hadis, 2010). Kekuatan oligarki ini akan melumat politik gerakan sosial dengan mudah. Sebab, suka-tidak suka, oligarki akan mengerahkan kekuatan uang untuk meruntuhkan kekuatan sosial, komunitas, dan gagasan dari kekuatan politik lawannya.
Kedua, kebiasaan politik musyawarah dalam masyarakat adat akan berhadapan dengan tendensi regulasi dari demokrasi liberal melalui pola one man one vote. Pada dimensi ini, kekuatan musyawarah adat dengan sendirinya akan terpecah. Praktik satu orang satu suara ini dengan sendirinya memparipurnakan kebanalitasan politik uang.
Ketiga, masyarakat adat dihadapkan pada masalah teknis. Ambil contoh, syarat KTP elektronik dan surat keterangan dari dinas kependudukan dan pencatatan sipil jika masyarakat adat ingin memiliki hak suara dalam pemilu. Fakta terbalik menunjukkan bahwa sebanyak satu juta anggota masyarakat adat yang tinggal di pedalaman tidak memiliki berbagai dokumen itu. Jadi otomatis suara mereka terbuang percuma.
Keempat, kendati ada banyak kisah sukses dari perjuangan masyarakat adat dalam politik elektoral, khususnya saat kader mereka mampu memenangi pertarungan di tingkat lokal, pada akhirnya mereka kerap lupa akan perjuangan komunitas. Akibat masalah laten ini, kader mengalami keterputusan/ketercerabutan dengan komunitas. Hal ini adalah masalah internal yang harus segera disiasati dengan baik dalam gerakan politik masyarakat adat.
Tentu masih ada banyak persoalan lain yang dihadapi oleh masyarakat adat dalam perjuangannya merebut kekuasaan dalam politik lokal. Untuk mengatasi keempat persoalan tersebut tentu bukanlah perkara dan pekerjaan mudah. Apalagi persoalan mengenai belum adanya KTP elektronik dan surat keterangan dari dinas kependudukan dan pencatatan sipil untuk masyarakat adat pedalaman agar memiliki hak pilih.
Persoalan semacam ini harus segera diadvokasi lebih intens lagi supaya hak pilih masyarakat adat tidak terbuang sia-sia. Sementara itu, dalam upaya melawan persoalan lainnya, berdasarkan pengalaman penulis, penentuannya ada pada komunitas itu sendiri. Artinya, seberapa besar kemauan komunitas untuk berjuang, bertarung mati-matian dalam politik elektoral. Jika kemauan itu ada, komunitas akan mampu melawan politik uang dan "menghukum: kader yang lupa akan akarnya".