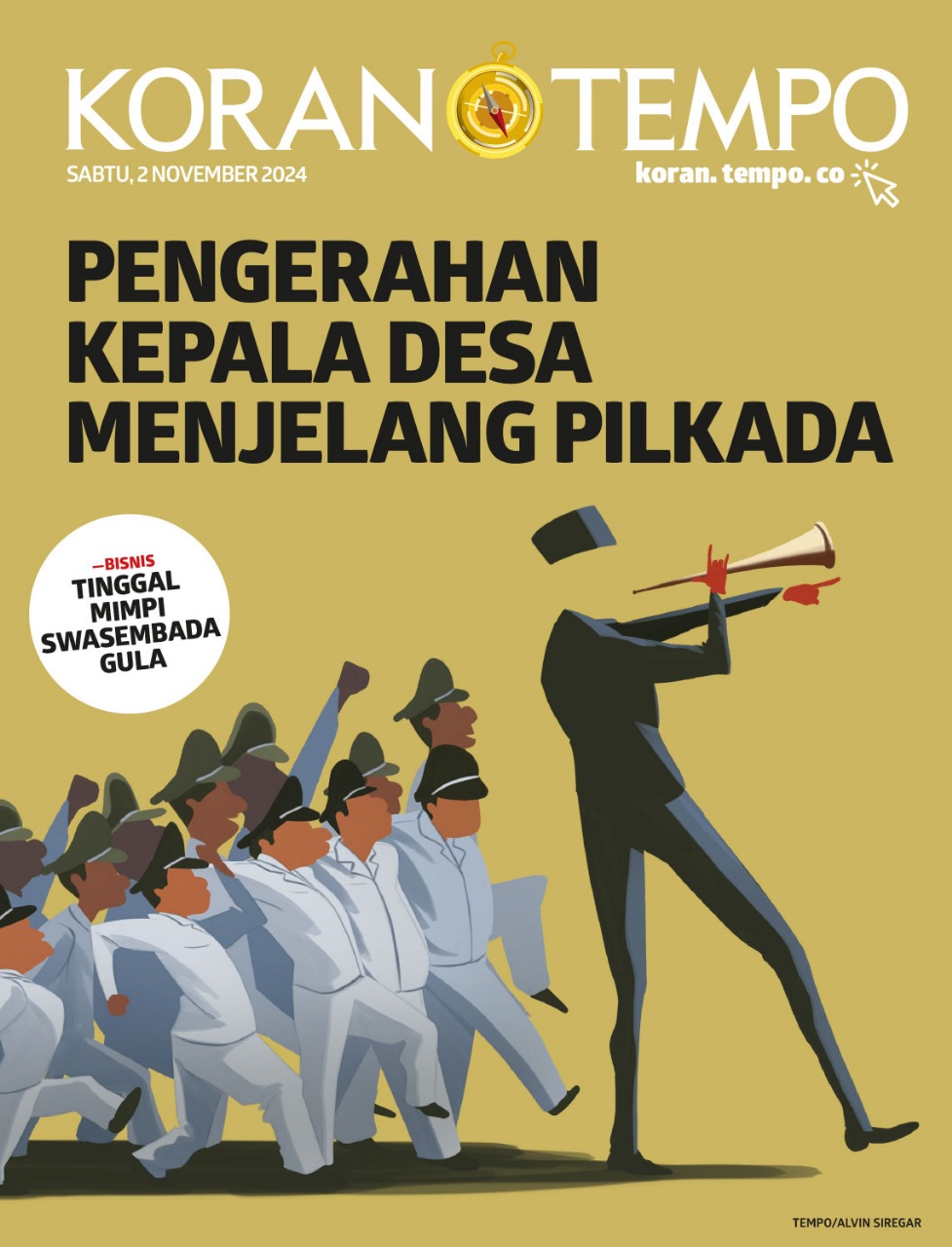Jaringan Korupsi Perizinan dan Kementerian Kelautan
arsip tempo : 173055086830.
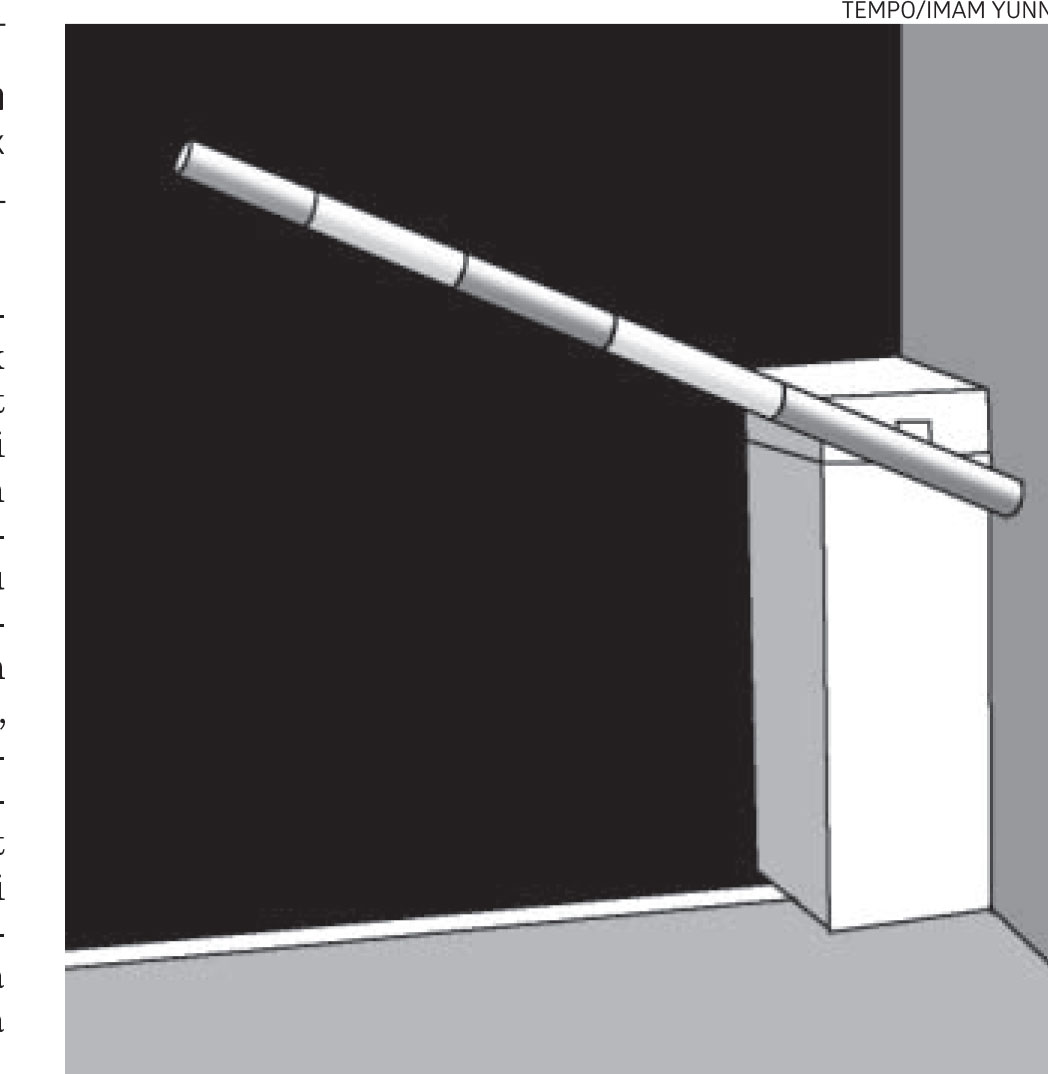
Peneliti Kebijakan Publik
Masyarakat sebenarnya tak perlu terkejut perihal korupsi di Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), karena praktik lancung itu masif terjadi dalam perizinan sumber daya alam di Indonesia. Sejak 2015, Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) sudah mendalaminya dan bahkan, lewat jalur pencegahan, Komisi sudah mencoba memberikan masukan kepada kementerian dan lembaga teknis, termasuk KKP.
Menga
...
Berlangganan untuk lanjutkan membaca.
Kami mengemas berita, dengan cerita.
 Manfaat berlangganan Tempo Digital? Lihat Disini
Manfaat berlangganan Tempo Digital? Lihat Disini