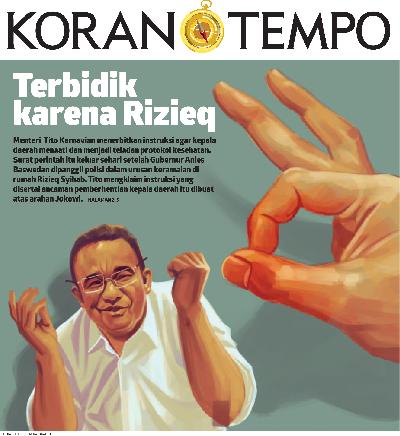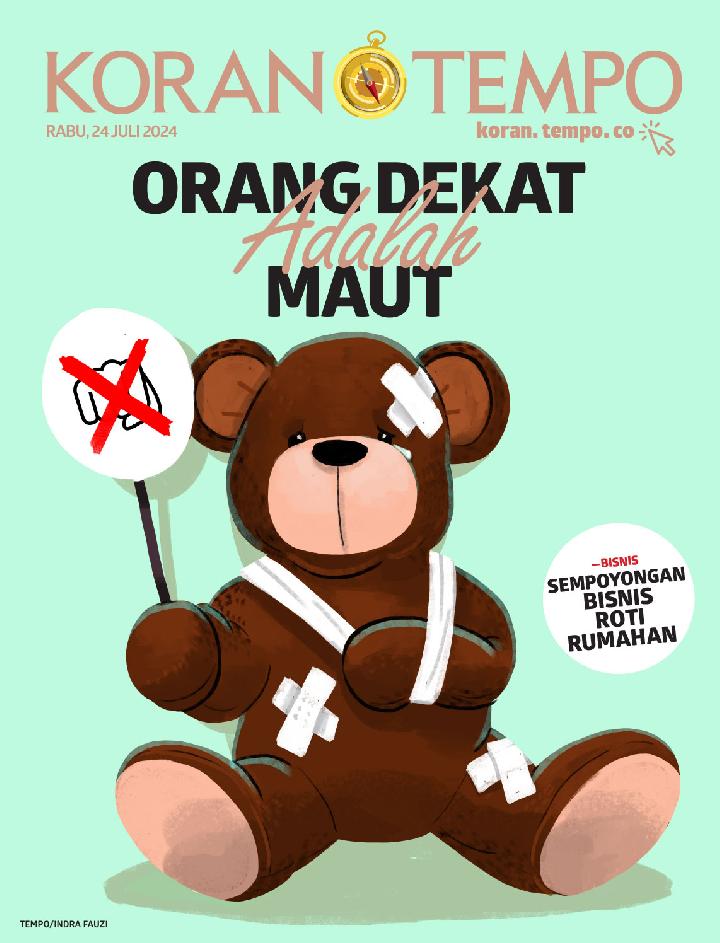Menguji Mahkamah Konstitusi
arsip tempo : 172204240073.

I D.G. Palguna
Mantan Hakim Konstitusi
Nemo judex in causa sua. Demikian sebuah maksim Latin yang secara harfiah berarti “tak seseorang pun dapat menjadi hakim bagi perkaranya sendiri”. Seorang hakim tidak mungkin bisa memutus suatu perkara secara adil jika ia memiliki kepentingan terhadap atau dalam perkara itu. Maksim itu kiranya tepat untuk menimbang dua permohonan pengujian, formal maupun materi, terhadap Undang-U...

Berlangganan untuk lanjutkan membaca.
Kami mengemas berita, dengan cerita.
 Manfaat berlangganan Tempo Digital? Lihat Disini
Manfaat berlangganan Tempo Digital? Lihat Disini