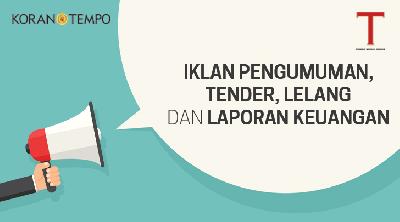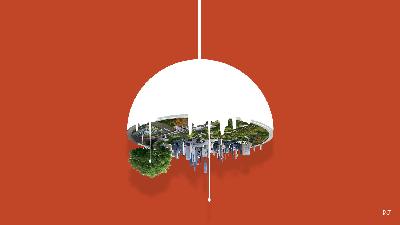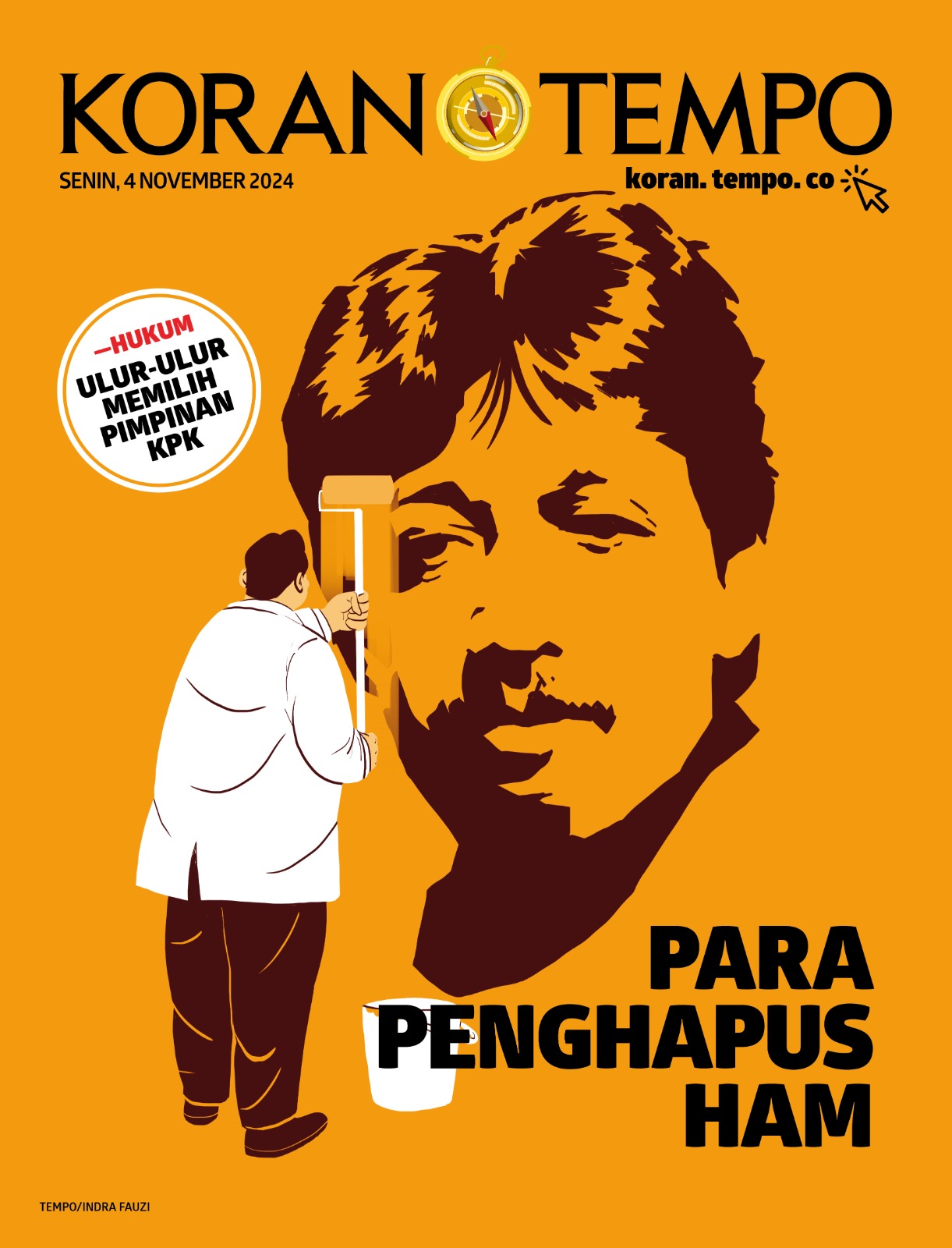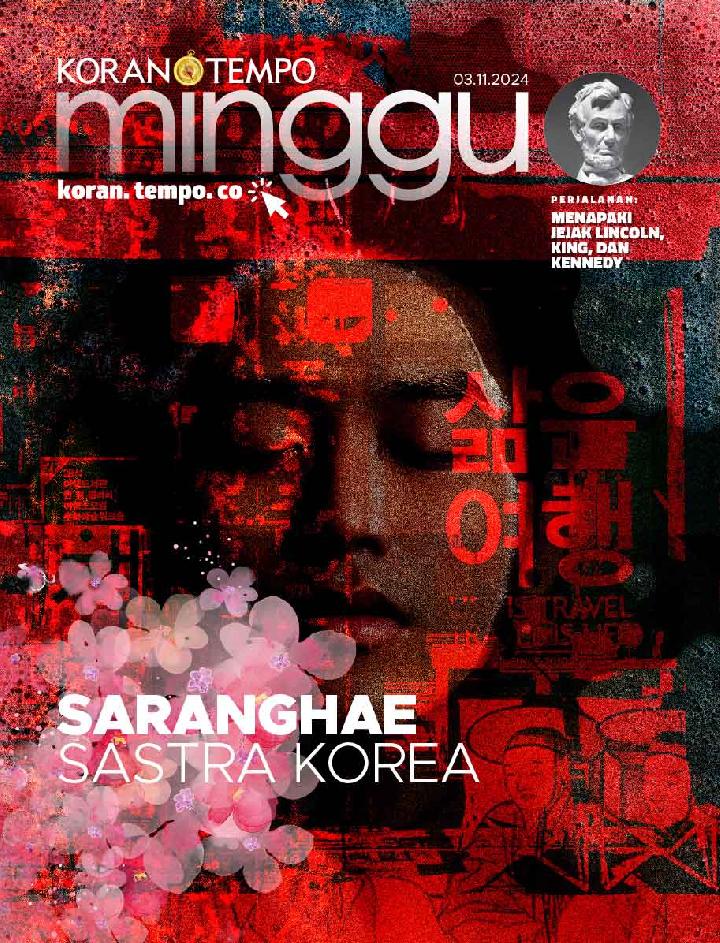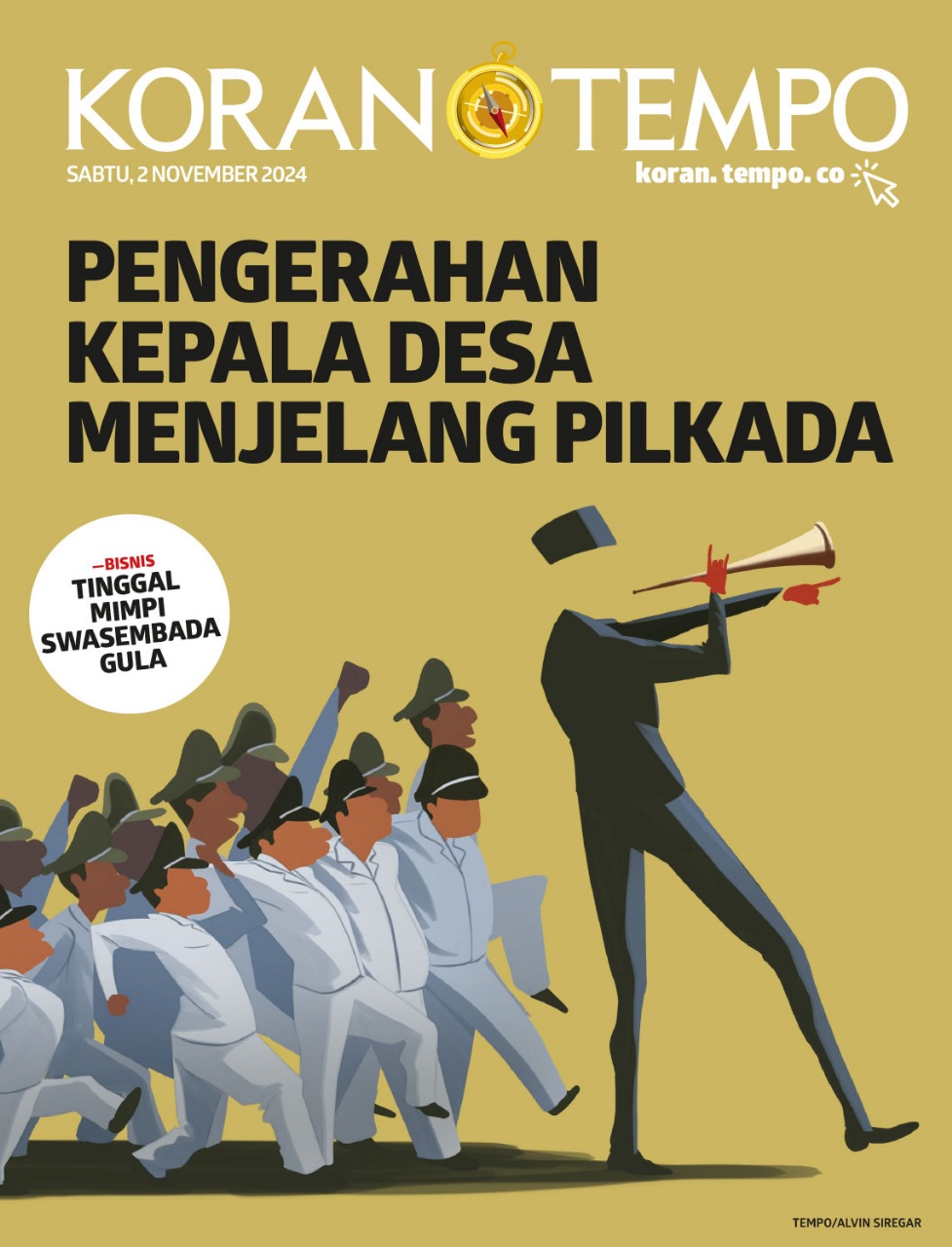Pendidikan Kontekstual Berbasis Kosmologi Kultural
Semua kebudayaan di dunia memuat eksistensi manusia dan relasinya dengan alam dalam narasi kosmologinya
arsip tempo : 173074415838.

Kita sedang memasuki era yang karakternya serba baru. Komponen-komponen “Dunia Baru” yaitu individu, kelompok, dan dunia seutuhnya, berinterrelasi dalam skala lokal hingga global; amat dinamis: aliran cepat dengan muatan besar, baik material, termasuk manusia, maupun immaterial seperti informasi dan falsafah hidup, yang meningkatkan laju perubahan. Ini meninggikan tingkat kebercampuran, khas sistem kompleks dimana terus bermunculan interrelasi rumit, multilevel, dan intens.
Perlunya Kemawasan Kultural Baru
Walaupun manusia sanggup memprediksi, momentum dinamik dan kompleksitas dewasa ini demikian tinggi sehingga ketidakpastian semakin inheren, bahkan memungkinkan luaran baru tak terduga. Pandemi Covid-19, musibah dunia yang dampaknya dahsyat pada semua aspek, telah memicu gaya hidup baru. Untuk bisa beradaptasi tanpa tertinggal, juga tidak terseret, kita perlu memahami mana yang substansial dan fundamental, mana pula trend sesaat, agar bisa kita urutkan prioritas suatu era. Ini memerlukan mindfulness dan strategi baru yang serius dalam merawat interrelasi untuk menjamin keberlanjutan yang baik dan adil.
Khusus manusia, keberlanjutan tidak cukup pada keberlangsungan hidup tetapi perlu memastikan pemajuan peradaban. Untuk mengupayakan bagaimana memenuhi syarat keberlanjutan terintegrasi ini, kita analisa dulu ekosistem dimana peran manusia prominen.
Keberlanjutan individual mensyaratkan pemenuhan hak untuk hidup berbahagia lahir batin, berelasi, mengembangkan diri sesuai aspirasinya, berpartisipasi dalam peradaban, serta diproteksinya diri dan nilai yang dianut. Keberlanjutan kelompok memerlukan pemenuhan hak untuk berasosiasi dalam bentuk keluarga, pertetanggaan, kesukuan, kepercayaan, budaya, negara, keprofesian, dan sebagainya, berkontribusi, dan menghidupkan nilai yang dijunjung.
Keberlanjutan lingkungan alam dikendalai oleh fakta bahwa: Bumi adalah rumah semua makhluk hidup; Bumi sebagai sumber hidup tidaklah tak terbatas, tetapi dipaksa memenuhi kebutuhan populasi dan keinginan manusia yang bertambah pesat, menyebabkan perubahan pola iklim global, degradasi lingkungan, punahnya banyak spesies, bertambahnya jenis penyakit. Kualitas hidup manusia, terutama yang kemampuan ekonominya rendah, banyak terkompromisasikan. Bumi memerlukan waktu panjang untuk pemulihan, sehingga banyak kerusakan alam tak sempat terpulihkan. Hukum manusia perlu mengindahkan hukum alam.
Anggota kelompok senantiasa menyeimbangkan antara kewajiban berkontribusi dan hak memperoleh manfaat seiring perubahan ekosistemnya. Juga terlihat bagaimana posisi manusia di alam: sebagai pemanfaat dan pelindung, atau penguasa dan perusak. Sebagai makhluk paling cerdas dan terampil manusia berkewajiban menjamin keberlanjutan semua penghuni bumi selama mungkin. Semua kebudayaan di dunia memuat eksistensi manusia dan relasinya dengan alam dalam narasi kosmologinya. Narasinya mirip di mana pun, termasuk dalam budaya di Nusantara, yaitu manusia dapat memanfaatkan alam, namun tak berkuasa mengaturnya sehingga bergantung pada kemurahannya untuk terus hidup, dan tugas manusia adalah menjaga keseimbangan alam.
Peran Penting Pendidikan Kontekstual
Indonesia negara besar, konstituennya heterogen dan tersebar, interkoneksinya kompleks, dengan tantangan memperkecil kesenjangan sosial, ekonomi, dan pendidikan yang menghambat pemajuan, sambil menjaga keanekaragaman budaya. Pertanyaannya: bagaimana pendidikan menyiapkan generasi penggerak Dunia Baru ini?
Indonesia mendengungkan budaya sebagai serat pemajuan peradaban karena kedalaman falsafahnya, kekayaan budayanya, yang berakar dan mewarnai nalar dan nurani dalam berbangsa. Namun disadari bahwa budaya bisa menjadi penyebab kelembaman, bahkan antitesis dari kemajuan, apabila kita luput memahami bagaimana budaya sebaiknya menyetir kita dalam peta dinamis dunia. Cultural commoning merumuskan common cause berdasarkan kesamaan sejarah, harapan, dan tantangan, lalu mengkonstruksi common strategy, untuk bergotong-royong membangun sambil terus menghormati dan menjaga keanekaragaman yang menjadikan Indonesia resilien.
Di mana budaya Indonesia dalam peta diri dan peradaban dunia? Pengenalan diri yang komprehensif mendorong refleksi terhadap lingkungan sebagai rujukan. Kita pilih empat elemen peradaban yang berperan dalam budaya Indonesia: Seni, menyelami ritme dinamis manusiawi untuk mengekspresikan persepsi, relasi, mimpi, frustrasi, kegelisahan; Sains, mencari-tahu relasi kausal fenomena alam, termasuk manusia, serta menjelaskan dan memprediksi kompleksitas dan dampaknya; Teknologi: wujud solusi untuk berbagai kebutuhan dan keinginan manusia; Komunikasi: berbagai bentuk esensi dan moda transfer nya dalam interrelasi. Keempat elemen ini mengenali kata-kata kunci yang sama, antara lain: kebutuhan, harapan, keindahan, perubahan, keseimbangan, kelayakan, kepantasan.
Bila kita ambil kata-kata kunci ini sebagai check points untuk membantu mengenali diri, ekosistem lingkungan, dan meletakkan diri dalam peta besar ekosistem, kita dapat ajukan pertanyaan serius tentang profil dan aspirasi diri, tentang peran diri pada upaya pemajuan ekosistem. Jawaban jitu memerlukan pertanyaan dinyatakan secara jernih (well-phrased, well-motivated) yang bisa dikontekstualisasi dalam aspek-aspek yang relevan, seperti budaya dan kepentingan praktis.
Persepsi akan realitas, cara pandang, dan motivasi krusial dalam bertanya. Pengalaman menunjukkan bahwa gagasan yang jernih berangkat dari pertanyaan yang jelas.
Mencoloknya disparitas kualitas hidup dan rusaknya relasi antar manusia dan antara manusia dengan lingkungannya menunjukkan kurangnya pemahaman akan aspek kausal dalam interrelasi itu dan ketidakbijakan penggunaan teknologi yang cenderung eksploitatif. Menyadari ini, kita perlu dididik bagaimana bertanya melalui bercermin.
Atas pertanyaan seperti inilah realitas hadir sebagai jawaban potensial untuk disusun menjadi pengetahuan, menjadi bagian pemajuan budaya, bukan informasi tak menentu dan berumur pendek. Untuk merealisasi keingintahuan dan aspirasi tak terbatas dan memoderasi kepentingan yang saling berkonflik elemen-elemen budaya berkelindan memainkan perannya.
Dimensi akal budi, mental, dan spiritual manusia mengelola tantangan dan solusinya agar terjaga keseimbangan di antara dimensi-dimensi tersebut, dengan respek, kepantasan, dan keindahan sebagai ukuran luhurnya budaya. Reformulasi pendidikan harus menguatkan kemampuan berpikir rasional, menghaluskan nurani, memperluas eksposur pada keanekaragaman, keberlimpahan sekaligus keterbatasan, serta kesempatan berpartisipasi positif atas kesadaran bahwa keberlanjutan diri memerlukan keberlanjutan komunal dan lingkungan alam.
*Penulis: Premana W. Premadi, Astronom