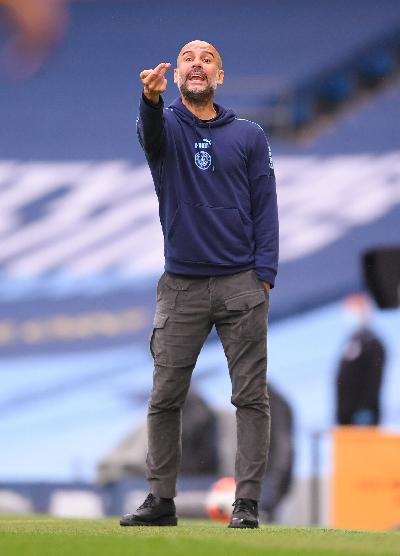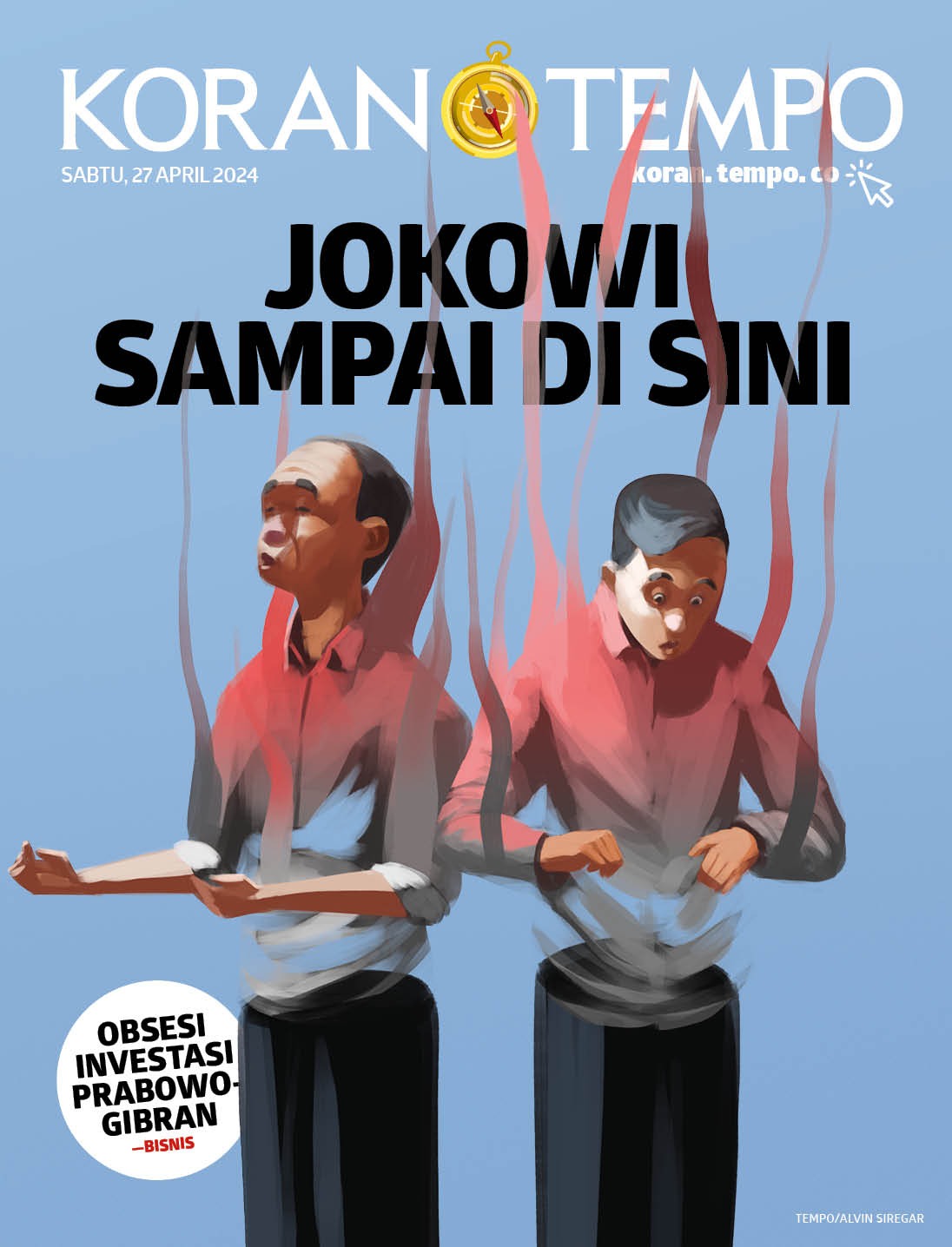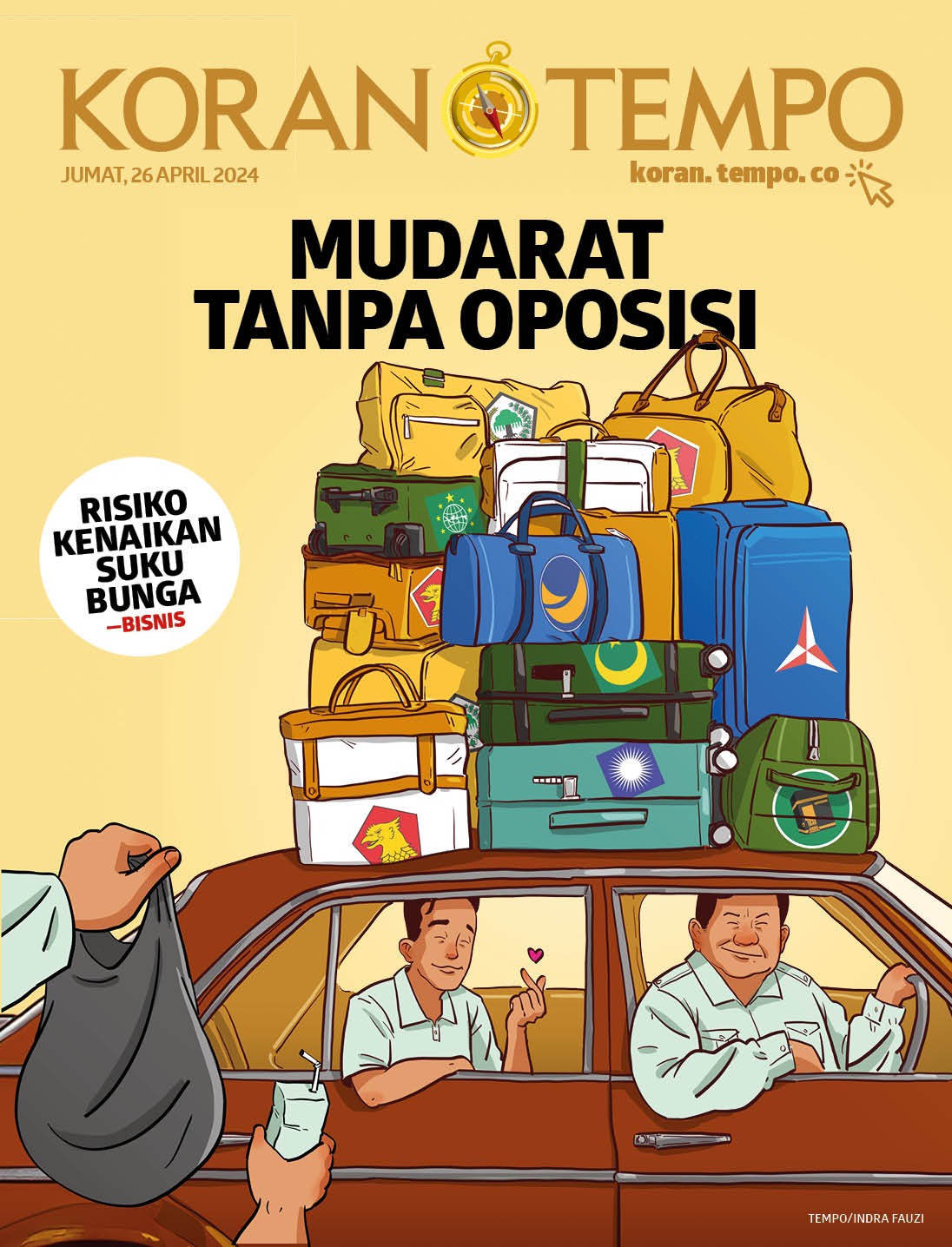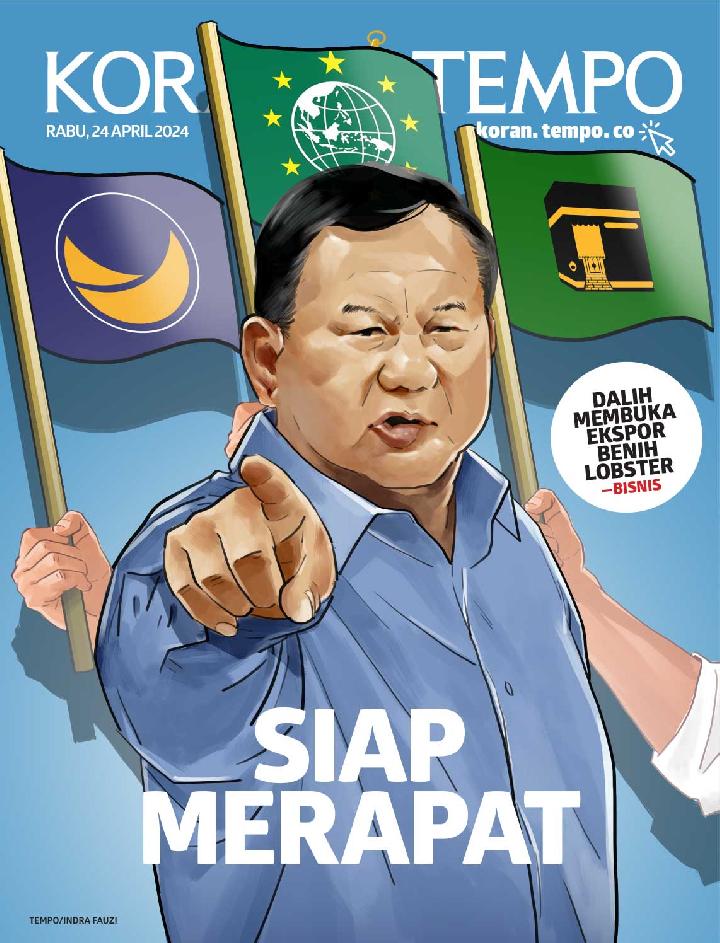Berdaya karena Dukungan Keluarga
arsip tempo : 171417491185.

Lima belas tahun lamanya Aning meninggalkan anaknya, Bagus, untuk bekerja di Brunei Darussalam. Di sana, ia menjadi asisten rumah tangga. Sejak kepergiannya pada 2003, Aning hanya bisa pulang ke kampungnya di Cilacap, Jawa Tengah, dua tahun sekali. Walau jarang mudik, Aning mengaku cukup beruntung. Sebab, ia tetap lancar berkomunikasi dengan Bagus yang dirawat kakek dan neneknya. “Alhamdulillah bos saya di Brunei sangat pengertian,&rd
...
Berlangganan untuk lanjutkan membaca.
Kami mengemas berita, dengan cerita.
 Manfaat berlangganan Tempo Digital? Lihat Disini
Manfaat berlangganan Tempo Digital? Lihat Disini