Salah Jalan Subsidi Tarif Kereta
Pengurangan subsidi tarif KRL Jabodetabek menunjukkan ketidakpahaman pemerintah mengelola transportasi publik. Tarif mesti naik.
arsip tempo : 172641755159.
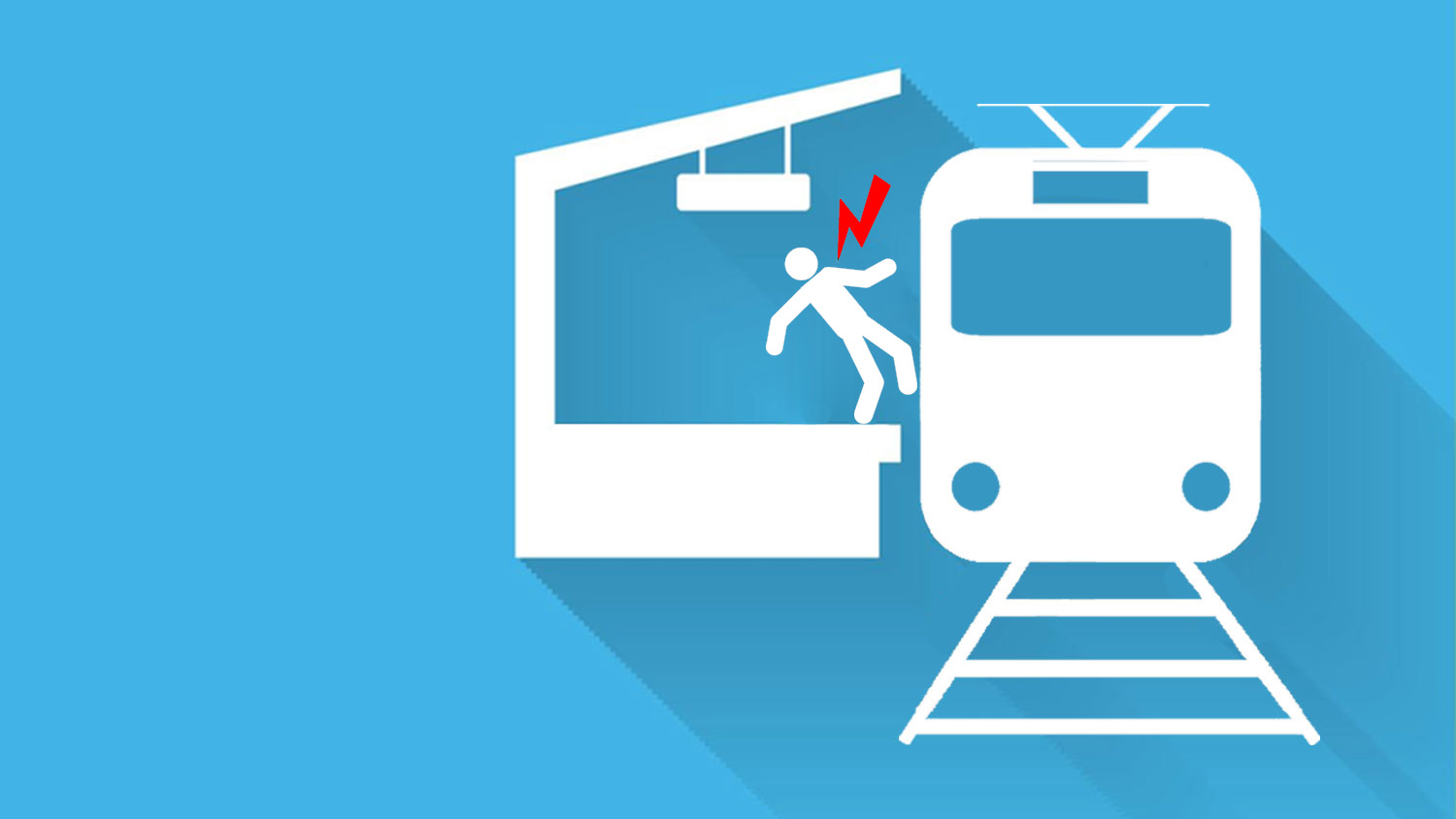
RENCANA pemerintah menaikkan tarif kereta rel listrik (KRL) Jakarta-Bogor-Depok-Tangerang-Bekasi dengan alasan agar subsidi tepat sasaran menunjukkan ketidakpahaman mengelola transportasi publik. Tarif KRL Jabodetabek jelas harus disubsidi karena moda transportasi ini merupakan angkutan massal yang menggerakkan ekonomi dan mengurangi emisi karbon.
Apalagi jika menaikkan tarif KRL itu dilakukan dengan menyeleksinya lewat nomor induk kependudukan (NIK). Dalam rencana pencabutan subsidi di Buku II Nota Keuangan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2025 itu, pemerintah berdalih subsidi tarif KRL selama ini dinikmati oleh golongan mampu.
Asumsi ini keliru sepenuhnya. KRL Jabodetabek dipakai oleh semua kalangan, sekitar 1 juta pekerja per hari yang tinggal di kota-kota aglomerasi Jakarta. Mereka adalah penggerak ekonomi. Karena itu, membedakan tarif berdasarkan golongan ekonomi justru menjadi tidak tepat sasaran. Seleksi memakai NIK juga akan membuat runyam karena mesin kartu kereta mesti mendeteksi NIK untuk distribusi tarif subsidi.
Gagasan memakai NIK untuk seleksi subsidi ini pasti datang dari pejabat yang tidak pernah naik kereta, mereka yang tak pernah merasakan umpel-umpelan di gerbong, atau antre di mesin kedatangan dan keberangkatan. Tanpa saringan NIK seperti sekarang saja, pada jam sibuk, penumpang mesti antre untuk masuk dan keluar stasiun.
Di mana-mana, subsidi transportasi umum bersifat universal. Tak ada pembedaan untuk penumpang berdasarkan golongan ekonomi. Sebab, pemakaian transportasi publik sudah seharusnya menjadi angkutan masyarakat kota untuk mencegah kemacetan dan polusi. Karena itu, seharusnya tarif angkutan umum disubsidi sebagai penghargaan bagi mereka yang beralih dari kendaraan pribadi.
Jika pun pemerintah sudah kewalahan menanggung subsidi KRL Jabodetabek, kenaikan tarif tanpa embel-embel subsidi salah sasaran. Tarif KRL sudah berlaku sejak 2016. Wajar pemerintah menaikkannya dari tarif Rp 3.000 per 25 kilometer pada tahun depan. Dengan inflasi dan pertumbuhan ekonomi, kenaikan tarif KRL bisa untuk menambal biaya operasi serta perawatan yang meningkat dari Rp 388 miliar menjadi Rp 2,4 triliun pada tahun lalu.
Namun, sebelum pencabutan subsidi itu, argumen pemerintah bahwa public service obligation (PSO) PT Kereta Api Indonesia sudah membebani harus diuji lebih dulu. PSO KAI Commuter hanya Rp 1,6 triliun dari total subsidi kereta secara keseluruhan sebesar Rp 2,5 triliun pada 2023. Angka ini tak sepadan jika dibanding subsidi kereta cepat Whoosh Jakarta-Bandung yang jadi tunggangan penduduk kelas menengah-atas sekitar Rp 100 ribu per orang.
Maka, ketimbang memangkas subsidi KRL yang jelas-jelas menjadi angkutan massal penduduk Jabodetabek untuk bekerja, pangkas saja subsidi Whoosh karena membebani APBN dan pemakainya bukan mayoritas warga negara. Lagi pula Whoosh telah menyandera PT KAI karena beban proyek kereta cepat ini menelan biaya Rp 112 triliun.
Menaikkan tarif KRL untuk menjaga mutu dan layanan kereta bukan sebuah aib, ketimbang menutupinya dengan embel-embel subsidi untuk orang miskin. Apalagi caranya memakai NIK yang diskriminatif berdasarkan kaya-miskin. Penyamaran kenaikan tarif ini bukan komunikasi kebijakan dengan masuk akal. Hanya melanggengkan populisme yang menipu.











