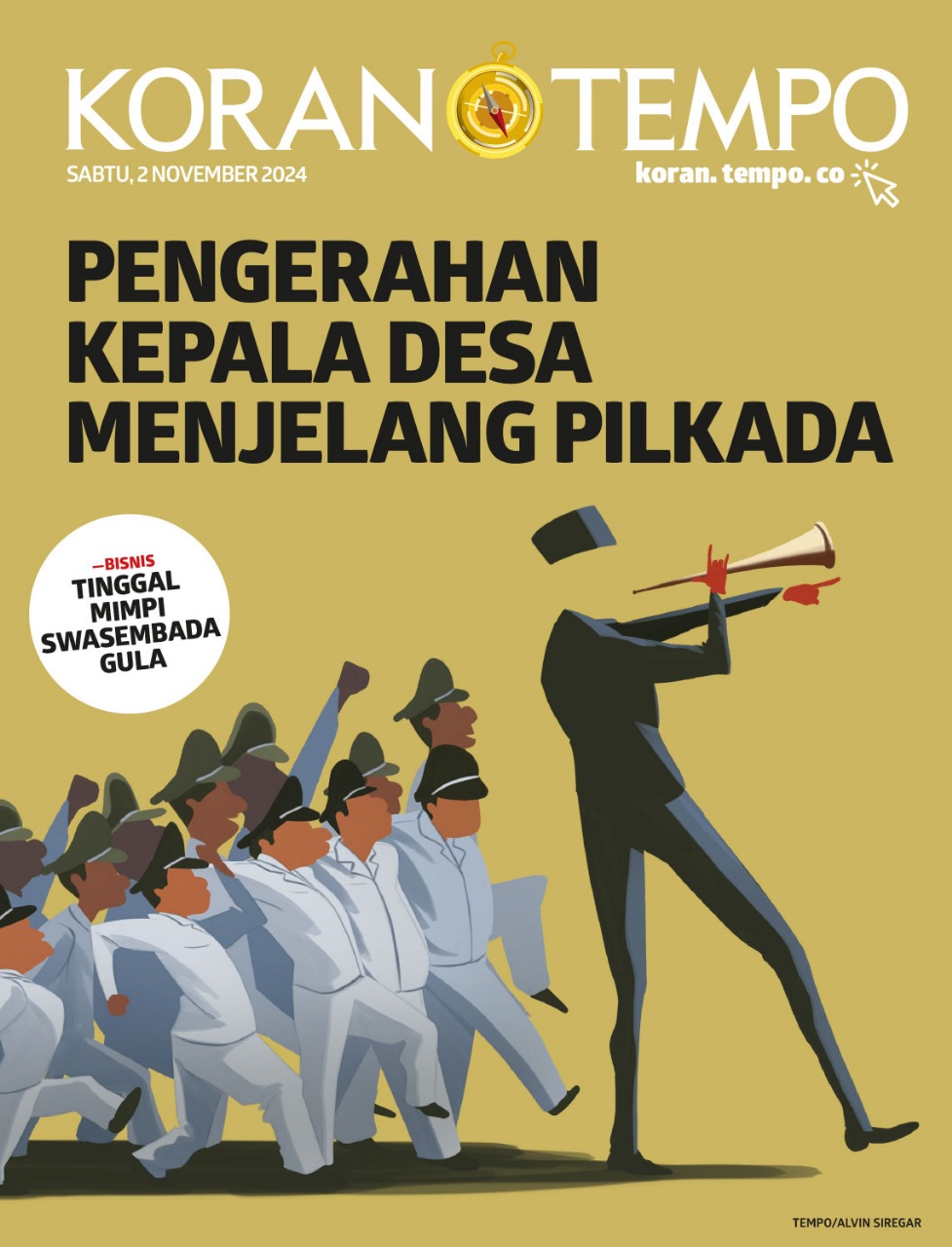Peran Koalisi Masyarakat Sipil untuk Pemilu Berkualitas
Peran masyarakat sipil di negara yang pemerintahannya mengarah ke otoritarianisme perlu diperkuat.
arsip tempo : 173057227632.

PADA konferensi Tata Kelola Platform Digital: Membangun Jaringan pada Skala Global di Dubrovnik, Kroasia, 17-19 Juni 2024, muncul satu pertanyaan dari perwakilan organisasi pendidikan PBB, UNESCO. Mereka ingin tahu bagaimana koalisi masyarakat sipil dapat berperan dalam mendorong terwujudnya kampanye pemilu berintegritas di ranah digital.
Dalam acara itu, saya berbagi panggung dengan kolega dari Afrika Selatan, Spanyol, Bosnia Herzegovina, Kenya, dan Kolombia untuk menjawab pertanyaan itu. Pembahasan dilakukan dalam satu panel yang secara spesifik membahas peran koalisi masyarakat sipil untuk mewujudkan moderasi konten dan kebebasan berekspresi di ranah digital, berdasarkan pengalaman masing-masing negara.
Pertanyaan tersebut juga sebetulnya menggelayut di benak saya dalam penerbangan dari Dubai ke Dubrovnik, sehari sebelum konferensi itu. Kepadatan kegiatan mengajar, penelitian, dan berbagai rapat di kampus membuat saya terlalu sibuk untuk menyiapkan materi. Tapi, demi menjawab pertanyaan itu, di atas pesawat yang melalui pegunungan tandus—yang konon menjadi lokasi pengambilan gambar serial Games of Thrones—benak saya seketika melayang ke Indonesia.
Saya teringat perjalanan selama lebih dari setahun memimpin koalisi masyarakat sipil yang terdiri atas 12 organisasi terdepan di negeri ini dalam riset dan advokasi mengenai kebebasan berekspresi di ranah digital.
Dalam satu tahun terakhir, saya mendapatkan kehormatan untuk bertemu, berbicara, dan bekerja sama dengan berbagai perwakilan platform digital, pemerintah, dan lembaga penyelenggara pemilu. Salah satu tujuan kami adalah mewujudkan ruang publik digital yang terbebas dari disinformasi demi pemilu yang berkualitas.
Dari pengalaman itu, setidaknya ada lima catatan keberhasilan dan kegagalan yang dapat saya sampaikan. Pertama, koalisi ini berhasil menyatukan masyarakat sipil yang memiliki fokus pada isu digital, meskipun secara ideologi dan pola gerakan berbeda satu sama lain.
Di antara 12 masyarakat sipil tersebut, ada kelompok yang moderat dan kolaboratif dengan pemerintah. Namun ada juga kelompok yang kritis dan konfrontatif terhadap pemerintah. Meski berbeda, mereka terbukti mampu bekerja sama dalam satu tujuan besar pemilu yang berintegritas.
Kisah ini dapat menjadi pelajaran bahwa, ketika ada kesamaan agenda yang mendesak dan penting, kolaborasi sangat mungkin diwujudkan. Meski begitu, ada satu hal yang masih jadi pertanyaan besar: apakah koalisi ini mampu bertahan untuk menyambut pemilu berikutnya? Terlebih koalisi ini masih bergantung pada satu sumber pendanaan tunggal yang sangat rentan bagi kelanjutan kerja riset dan advokasi.
Kedua, koalisi ini berhasil mempertemukan dan membangun dialog untuk menyamakan persepsi di antara pemangku kepentingan, mengenai pentingnya tanggung jawab bersama untuk menciptakan ruang publik yang bebas dari hoaks dan berbagai disinformasi lainnya. Pertemuan dan dialog itu dilakukan dalam satu pertemuan kolektif maupun secara terpisah dengan masing-masing platform digital.
Keberhasilan tersebut bisa dibilang baru permulaan karena dialognya masih berkisar pada topik sangat umum. Antara lain soal pentingnya ruang digital yang sehat untuk pemilu dan demokrasi. Persamaan persepsi itu perlu dilanjutkan dalam satu program bersama yang konkret dan berdampak nyata.
Ketiga, koalisi berhasil melakukan proses pemantauan kampanye pemilu yang kelak akan berguna sebagai catatan pengawasan penyelenggaraan pemilu berikutnya. Namun penelitian yang serius memerlukan waktu untuk membangun teori, mematangkan metode, mendapatkan hasil, untuk kemudian melakukan analisis dan menuliskannya.
Begitu hasil penelitian rampung dituliskan dalam laporan yang dapat disebarkan kepada publik secara luas, pemilu telah berakhir. Hasil pemilu juga pelanggarannya sudah tak mungkin diubah lagi. Ke depan, penggunaan teknologi perlu diarahkan pada upaya preventif mendeteksi konten ilegal dan memberi respons cepat sebelum konten itu viral.
Perlu ada satu lembaga independen yang terdiri atas gabungan berbagai pihak. Lembaga ini bisa diisi oleh para akademikus, tokoh masyarakat sipil, dan jurnalis yang bebas dari kepentingan partisan untuk merespons dan memberi rekomendasi secara cepat.
Keempat, koalisi ini berhasil mengajak serta melatih sekelompok anak muda di dua kota, Semarang dan Yogyakarta, untuk berpartisipasi dalam melakukan pengawasan kampanye pemilu. Namun saya menyadari bahwa jumlah peserta pelatihan itu masih sangat jauh dari kata cukup. Ke depan, pelatihan bagi pengawas pemilu harus menjangkau 504 kabupaten/kota di Indonesia agar pengawasan pemilu dapat berjalan jauh lebih maksimal.
Upaya pengawasan oleh publik ini diperlukan untuk mengimbangi ratusan juta konten yang membanjiri ruang publik digital Indonesia. Kita tahu, pada masa kampanye, perang siber antar-para kontestan pemilu yang terdiri atas tiga pasangan capres-cawapres dan ribuan calon legislator terjadi begitu masif.
Kelima, koalisi juga berhasil mengajak kontestan pemilu duduk bersama dan menyepakati kode etik kampanye pemilu yang berintegritas. Kode etik itu antara lain berisi komitmen untuk tidak menggunakan pasukan siber, kecerdasan artifisial, disinformasi, dan ujaran kebencian.
Kesepakatan itu kemudian diiringi dengan penandatanganan komitmen yang difasilitasi Badan Pengawas Pemilu, serta dihadiri perwakilan seluruh pasangan calon presiden dan wakilnya, partai politik peserta pemilu, sampai platform digital. Sayangnya, hasil yang baik itu rupanya tak berdampak nyata. Dokumen itu hanya menjadi kesepakatan di atas kertas. Pada kenyataannya, pelanggaran masih banyak dilakukan oleh hampir semua kontestan pemilu dalam kampanye mereka di ranah digital.
Karena itu, agenda selanjutnya yang harus berjalan adalah memastikan para kontestan pemilu selanjutnya benar-benar mematuhi kode etik yang telah mereka sepakati. Pengenaan hukuman yang menimbulkan efek jera berdasarkan pada bukti kuat mungkin perlu dipertimbangkan.
Sebagaimana dijelaskan dengan sangat baik oleh Daron Acemoglu dan James Robinson (2020) dalam The Narrow Corridor, kebebasan dan demokrasi merupakan satu jalur sempit yang membutuhkan perimbangan kekuatan antara negara dan masyarakat sipil. Peran masyarakat sipil dibutuhkan untuk mengawal kekuatan negara, terutama di negara-negara yang mengalami kemunduran demokrasi dan kecenderungan kembali ke arah otoritarianisme seperti Indonesia.
Masyarakat sipil yang lemah tidak hanya membahayakan demokrasi, tapi juga akan membuat otoritarianisme semakin kuat. Di sinilah koalisi masyarakat sipil yang mendorong terwujudnya ranah digital yang bebas dari kabar bohong dan disinformasi politik perlu terus didukung dan diperkuat. Hanya dengan ruang publik yang sehat, yang berisi informasi yang benar, warga negara akan mendapatkan pertimbangan akurat untuk memilih dengan benar demi terwujudnya pemilu yang berkualitas.