Tarik-Ulur Revisi Undang-Undang ITE
Pasal-pasal dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) bermasalah serta dapat menimbulkan ketidakpastian hukum. Banyak korban berjatuhan karena pasal karetnya.
arsip tempo : 171430824259.
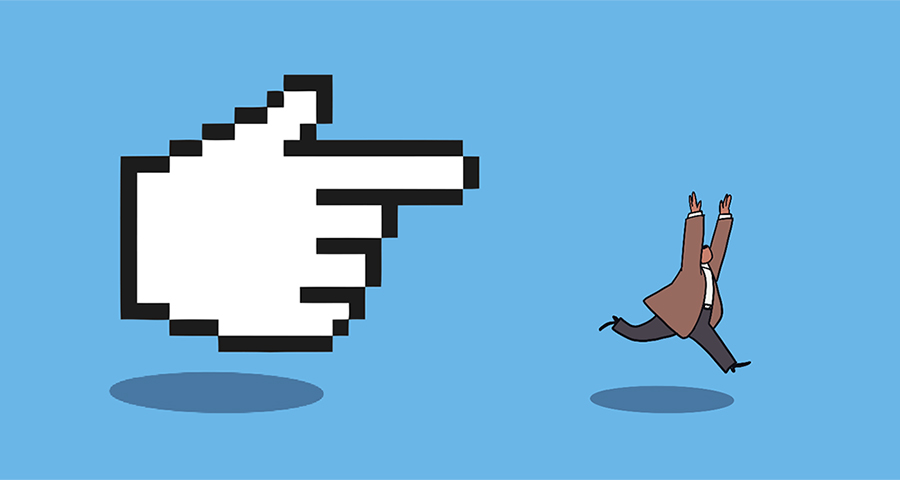
Usman Hamid
Pendiri Public Virtue, pengajar Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera
Banyak pihak berargumen bahwa Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) tidak perlu direvisi, karena sebenarnya "di atas kertas" isinya sudah baik. Kenyataannya, "di atas kertas" saja undang-undang itu masih banyak kekurangan, apalagi ketika melihat penerapan di lapangan.
Pemerintah harus membuka mata untuk memastikan bahwa penerapan UU ITE tidak men
...
Berlangganan untuk lanjutkan membaca.
Kami mengemas berita, dengan cerita.
 Manfaat berlangganan Tempo Digital? Lihat Disini
Manfaat berlangganan Tempo Digital? Lihat Disini











