Logika Bocah Kosong
Pemilu 2024 diwarnai pertunjukan kebodohan yang menjungkirbalikkan nalar. Publik dianggap sebagai bocah kosong yang tak mampu berpikir logis.
arsip tempo : 173057247933.
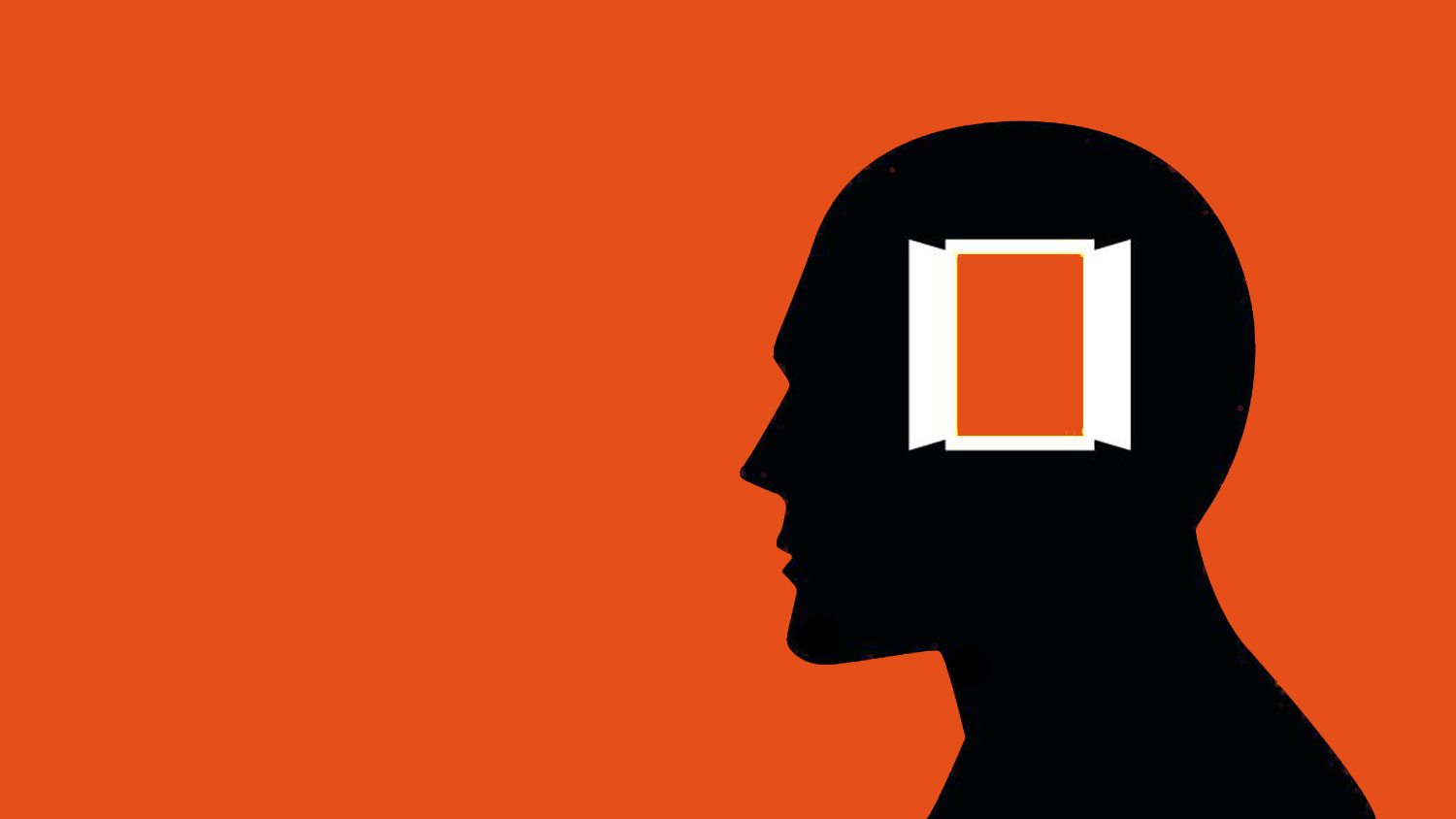
Nanang Haroni
Pengajar Ilmu Komunikasi Universitas Al Azhar Indonesia
Pemilihan umum usai sudah. Hiruk-pikuk kampanye pun berlalu. Tersisalah percakapan tak berujung mengenai dugaan pelanggaran dari jenis yang "tak dianggap" hingga dugaan praktik abuse of power. Siapa yang senang dengan kemenangan yang berasal dari proses penuh masalah? Pihak yang kalah ataupun menang sekalipun tak akan nyaman. Tapi kita juga tahu, banyak yang berusaha "mengajari" semua orang segera menerima kenyataan dan melupakan semuanya.
Apa itu jadi masalah? Tentu. Sikap semacam itu cacat secara nalar. Alih-alih frustrasi, kita butuh sebanyak mungkin ruang refleksi atas suguhan debat akrobatik para politikus yang arahnya seolah-olah ingin melupakan masalah-masalah dalam proses pesta demokrasi.
"Terima saja kekalahan." Demikian, misalnya, para pendukung pihak yang menang berujar. Kita tahu bahwa ini simplifikasi persoalan. Ia benar sebagai sebuah nasihat, tapi bisa sangat fatal ketika dijadikan alas untuk konteks sikap tertentu.
"Sudahi saja perdebatan. Kita cari win-win solution." Ini ungkapan lain yang tak kalah simplifikatif. Sebuah cara menghindari upaya-upaya lurus dan sehat untuk mengurai persoalan. Padahal upaya-upaya tersebut seharusnya memang tidak selalu bermakna menjatuhkan, merebut, dan menolak kekalahan. Ini justru tentang bagaimana membangun hidup bersama dalam keadaban. Memastikan setiap kesalahan dijadikan pelajaran bersama serta menegaskan pengharapan menjadi bangsa yang siap menjalankan demokrasi secara dewasa dan bernalar dapat segera terwujud.
Memang, ketika pertikaian elite berlanjut, rakyat kembali sibuk dengan urusan sehari-hari. Bahkan tak sedikit yang tidak peduli siapa menang-siapa kalah agar suasana panas tidak terus-menerus menghambat aktivitas keseharian mereka. Dari kondisi psikologis demikian, simplifikasi-simplifikasi tersebut ditebalkan. Persis di situ pula masalahnya.
Saat satu pihak mengesampingkan masalah-masalah yang terjadi dengan argumen rakyat ingin segera tenang, kita seperti menyaksikan akrobat "bocah kosong" yang eksploitatif. Fenomena "bocah kosong" populer dalam interaksi media sosial saat ini. Istilah ini merujuk pada sosok-sosok—umumnya generasi Z—yang kurang pengetahuan dan sulit mencerna pesan dengan alur pikir logis. Meski bermakna peyoratif, istilah "bocah kosong" seolah-olah dirayakan sebagai capaian mengkapitalisasi aspek dominan hiburan audio-visual: kelucuan. Dan hal itu rupanya berhasil.
Ironisnya, dunia para "bocah kosong" dan pasar media sosial yang membesarkan mereka juga merupakan ceruk yang menginspirasi perjalanan kampanye calon presiden dan wakil presiden pada Pemilu 2024. Begitu banyak sumber daya diarahkan untuk menaklukkan mereka, kelompok gen Z. Salah satu pasangan bahkan mengambil jargon yang berasal dari dan tepat menyentuh "kekosongan" itu: "gemoy".
Pertunjukan Kebodohan
Kapitalisasi fenomena "bocah kosong" dapat dikatakan sebagai pertunjukan stupidity atau kebodohan (Ronnel, 2023). Relatif mudah memahami istilah pintar sebagai konsep psikologis kecerdasan. Tapi, seperti kata Hayman (Why Smart People Can Be So Stupid, 2022), bodoh atau kebodohan tampaknya tidak memiliki padanan teknis yang jelas dalam teori psikologi. Kebodohan dapat menjadi properti dari suatu tindakan, perilaku, negara, atau orang.
Kebodohan utamanya bukan tentang kemampuan kognitif seseorang yang sulit bernalar—sebagaimana para kreator konten dan televisi meletakkan definisi "bocah kosong". Kebodohan sering berkaitan dengan pilihan tindakan dan perilaku yang diambil seseorang (de Vries, 2023), termasuk, misalnya, mengeksploitasi "kelucuan" dari kepolosan para remaja "kosong". Jadi stupidity akhirnya soal perilaku yang justru sering merujuk pada orang pintar. Lalu bodoh atau kebodohan, dalam konteks demikian, tidak berlawanan dengan pintar atau kepintaran. Lawannya, ya, bijak atau kebijakan.
Donald Trump dalam pemilu Amerika Serikat (2016) disebut banyak orang telah mengambil jalan ini. Ia memainkan peran sebagai demagog populis yang mengkhotbahkan doktrin-doktrin yang bahkan dia sadari tidak benar. Sebab, ia yakin banyak orang mudah tertipu.
Masalahnya, model kampanye dan jalan politik Trump yang diakui penuh dengan jualan kebodohan itu justru banyak ditiru. Termasuk dalam pentas politik kita hari. Kita sudah melalui perjalanan pemilu yang diwarnai bermacam tindakan dan peristiwa yang melukai demokrasi. Wakil presiden ke-10 dan 12, Jusuf Kalla, bahkan menilai pemilu kali ini yang terburuk dalam sejarah demokrasi Indonesia (Tempo.co, 8 Maret 2024).
Tetap saja hingga hari ini segala hal yang seharusnya terang masih abu-abu, dengan dibalut akrobat kata para aktor dalam mabuk kemenangan. Debat kubu-kubu yang berlawanan tentang banyak hal di media tidak menjadi ruang pendidikan yang mendorong warga makin sadar dan bijak, melainkan hanya serupa panggung rasionalisasi mentereng para pesilat lidah menyembunyikan fallacy dari kesadaran publik awam. Soal banyaknya masalah dalam pemilu, suara puluhan kampus yang merupakan garda terdepan penjaga kejernihan berpikir serta nilai-nilai kejujuran bukan hanya tak diterima, tapi juga dicurigai dan dituding sebagai gerakan politis yang merongrong kekuasaan.
Lengkap rasanya kita melihat motif di balik pertunjukan kebodohan para tokoh politik dan pejabat negara belakangan ini. Dari kecenderungan mengutamakan kepentingan pribadi-kelompok, kecenderungan overconfidence, bias kognitif, tekanan, mental atau emosi, keterampilan sosial rendah, ambisi, hingga keengganan bersikap jujur.
Entah kapan pertunjukan-pertunjukan kebodohan ini akan berakhir. Tentu kita tak boleh berhenti berharap suatu saat akan tumbuh praktik berpolitik dan bernegara yang benar-benar penuh kewarasan serta menjunjung tinggi keadaban. Semoga kelak semua pihak menyadari—semoga begitu—bahwa rakyat bukanlah "bocah-bocah kosong" yang akan terbuai oleh keputusan serta tindakan dengan argumen rapuh dan manipulatif. Setidaknya tidak dalam waktu lama.











