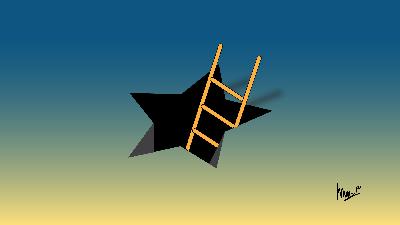Paradigma Lama Perubahan Otonomi Khusus Papua
arsip tempo : 173077998142.
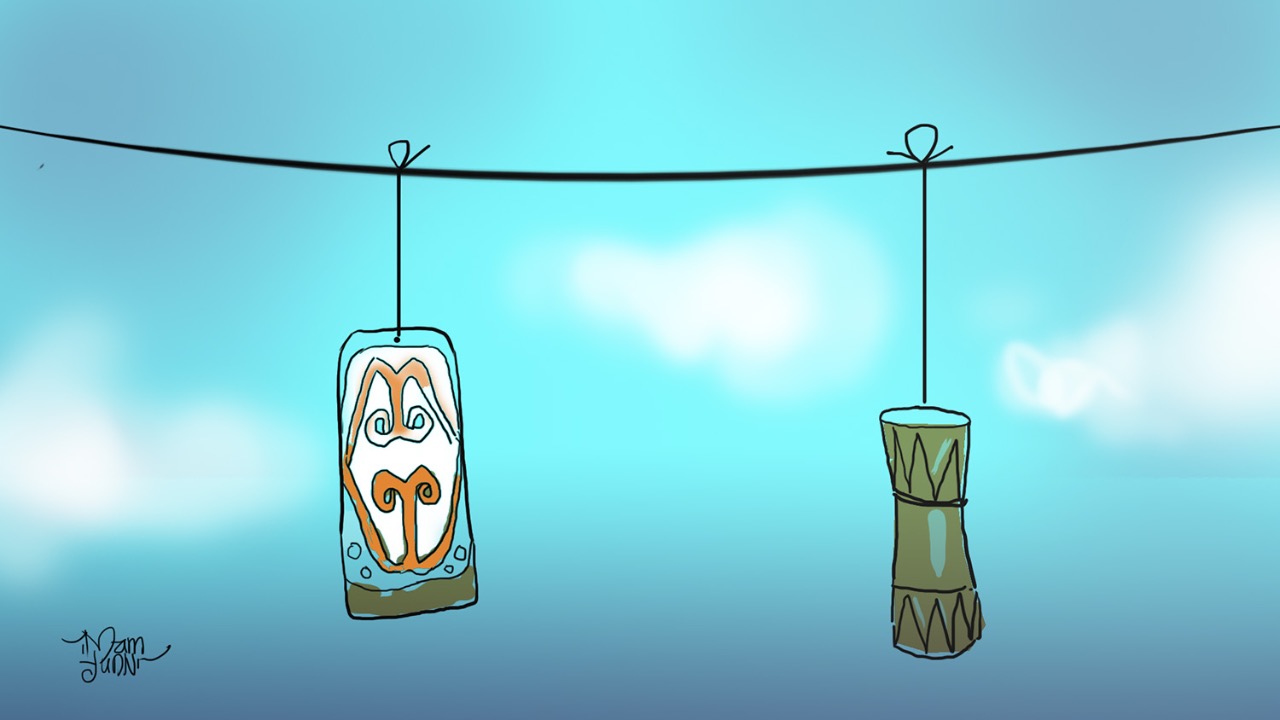
Frans Maniagasi
Anggota Tim Asistensi Undang-Undang Otonomi Khusus Papua 2001
Pada 11 Januari 2021 saat pembukaan masa sidang Dewan Perwakilan Rakyat tahun ini, pemerintah secara resmi menyerahkan surat Presiden Joko Widodo beserta lampiran rancangan revisi Undang-Undang Otonomi Khusus Papua. Ada beberapa hal yang patut menjadi sorotan yang layak diketahui oleh masyarakat, terutama rakyat Papua, yang menjadi subyek dan obyek dari pemberlakuan rev...

Berlangganan untuk lanjutkan membaca.
Kami mengemas berita, dengan cerita.
 Manfaat berlangganan Tempo Digital? Lihat Disini
Manfaat berlangganan Tempo Digital? Lihat Disini