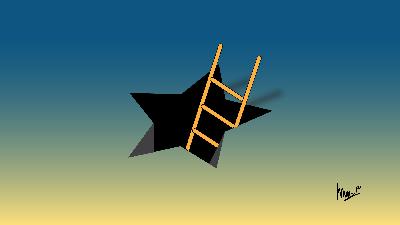Tebak Buah Manggis Kapolri Baru
Tidak terangnya sikap Presiden Joko Widodo soal kriteria Kapolri baru yang dia inginkan memberi ruang bagi para kandidat untuk bermanuver dengan berbagai cara.
arsip tempo : 171357651023.

Simpang-siur kabar penunjukan calon Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) pengganti Jenderal Idham Azis, yang pensiun pada 1 Februari nanti, tak perlu terjadi kalau prosesnya berlangsung patut dan transparan. Tidak terangnya sikap Presiden Joko Widodo soal kriteria Kapolri baru yang dia inginkan memberi ruang bagi para kandidat untuk bermanuver dengan berbagai cara.
Aturan yang menyebutkan pengangkatan Kapolri baru sepenuhnya hak p
...
Berlangganan untuk lanjutkan membaca.
Kami mengemas berita, dengan cerita.
 Manfaat berlangganan Tempo Digital? Lihat Disini
Manfaat berlangganan Tempo Digital? Lihat Disini