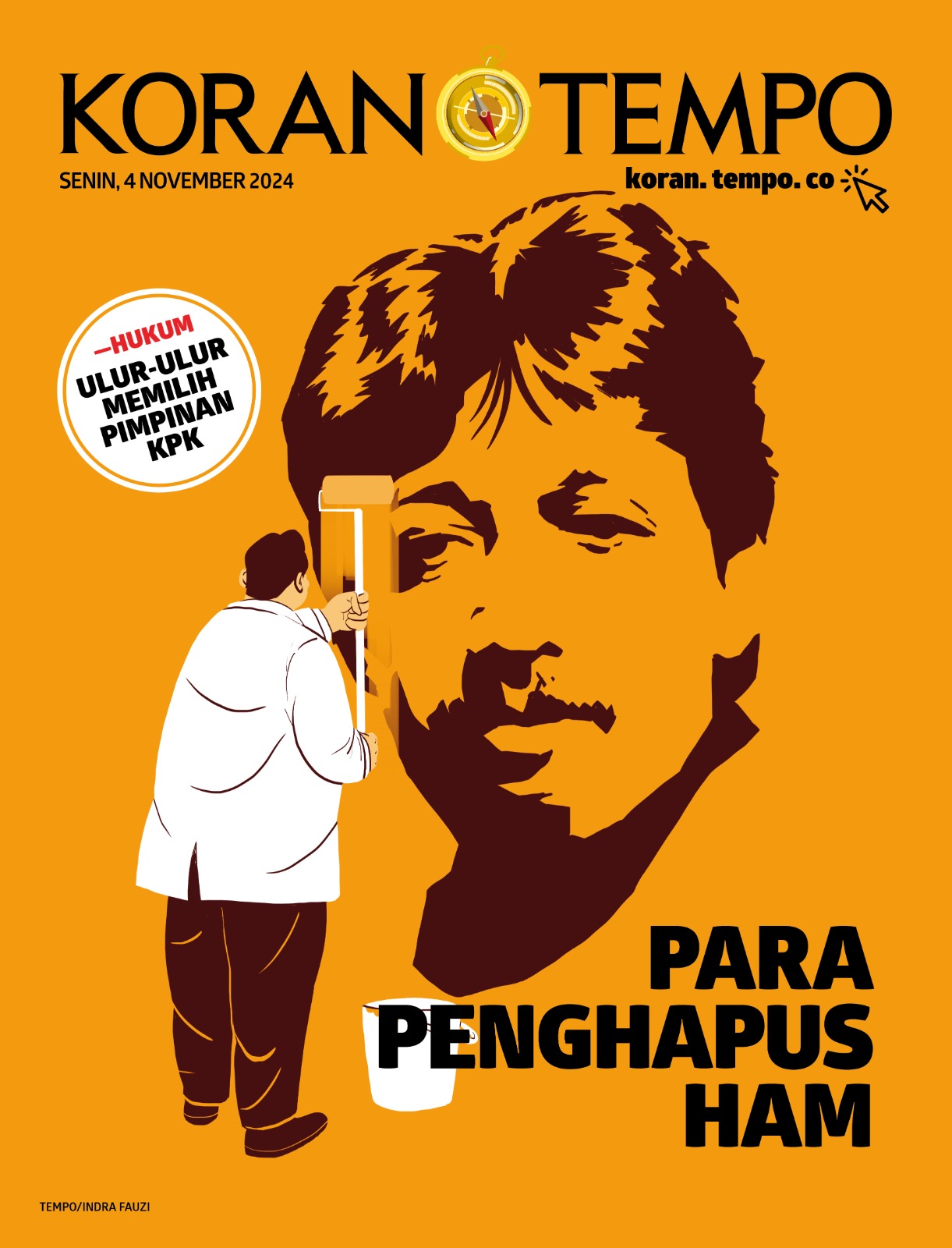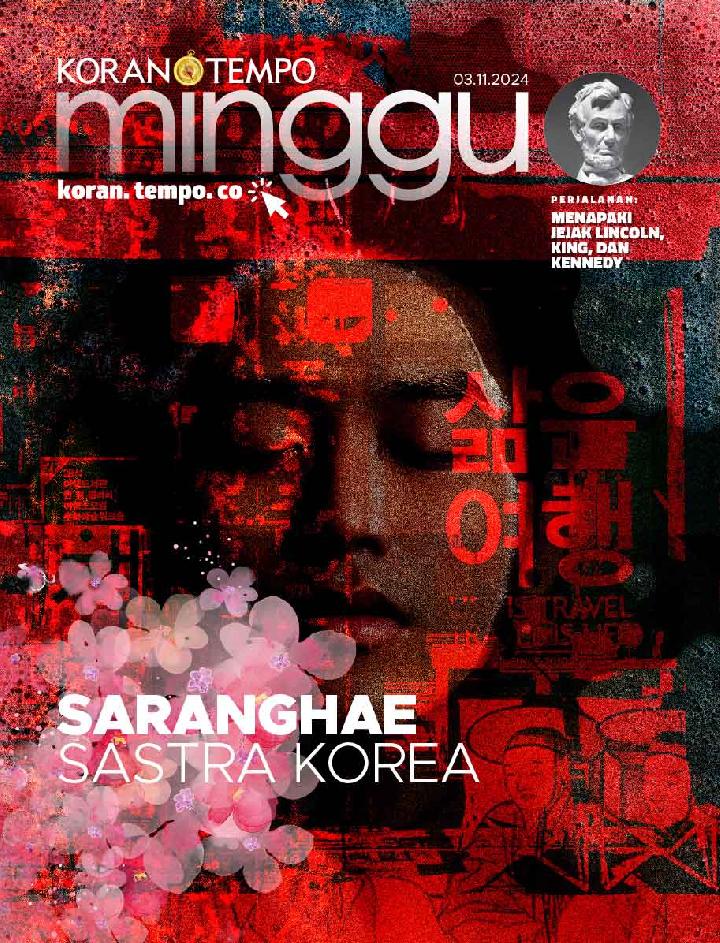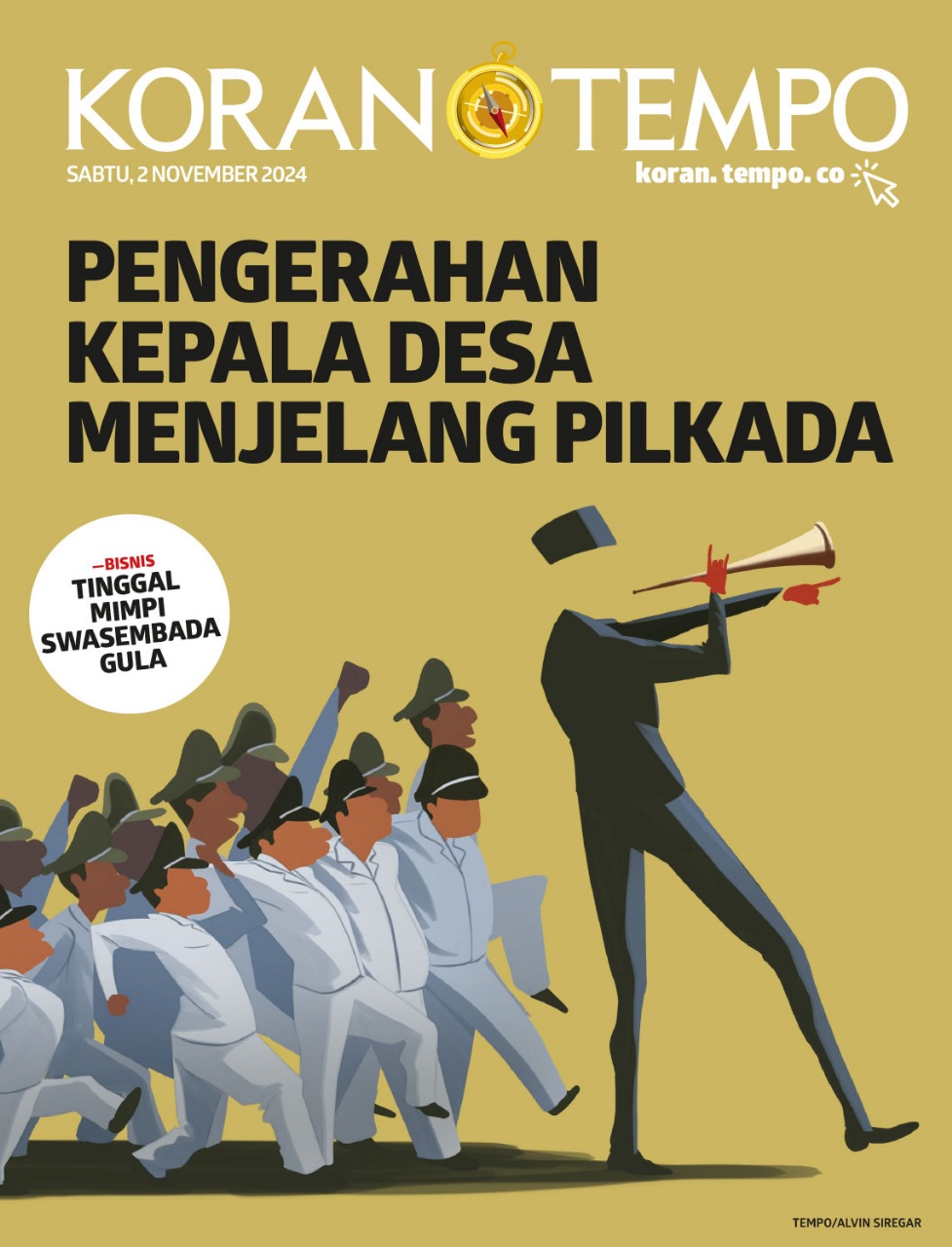Ekosistem Festival Seni di Indonesia: Bertumbuh Bersama dan Memupus Pemusatan
Melalui UU Pemajuan Kebudayaan, negara tidak lagi menguasai seluruh pelaksanaan produksi kebudayaan dari hulu ke hilir
arsip tempo : 173074304479.

Ajang kebudayaan seperti festival seni, pasca diresmikannya Undang-undang nomor 15 tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan (selanjutnya disebut UU Pemajuan Kebudayaan), telah bertransformasi menjadi katalisator dampak-dampak baik dalam kehidupan masyarakat. Pertumbuhan ekonomi menjadi salah satu dampak baik itu. Keseluruhan aspek festival seperti persiapan, produksi, penyelenggaraan dan apresiasi festival dapat menggerakkan roda perekonomian lokal pada daerah di mana festival itu berlangsung. Sebagai sebuah wahana yang mempertunjukkan pencapaian dan inovasi produksi seni, festival tidak hanya menyumbang perekonomian melalui aktivitas apresiasi dan konsumsi karya seni di dalamnya, melainkan juga berdampak ganda dalam hal mendorong usaha-usaha kecil-menengah yang menyokong penyelenggaraan festival seperti penginapan, kuliner, transportasi lokal, persewaan alat, dan seterusnya. Variabel-variabel ekonomi itu telah dipahami oleh banyak pemangku kepentingan baik pusat maupun daerah.
Namun, pertumbuhan ekonomi bukanlah satu-satunya dampak yang diharapkan dari pemajuan kebudayaan. Majunya kebudayaan suatu negara juga diharapkan berdampak pada meningkatnya nilai kewargaan yang mendorong kohesi-inklusi sosial, pemerataan kesejahteraan, kelestarian lingkungan, dan tentunya keberagaman imajinasi tentang sebuah bangsa. Maka dari itu pemajuan kebudayaan pada tataran kebijakan, pelaksanaan produksi kebudayaan dan interpretasi atas produksi kebudayaan memang tidak seharusnya dimonopoli seluruhnya oleh negara.
Monopoli ini akan berpotensi mengembalikan karakter kebijakan budaya yang terpusat khas Orde Baru, yang menempatkan pemajuan kebudayaan hanya sebagai piranti untuk menjaga stabilitas kekuasaan. Kebijakan budaya seperti ini semata-mata mengharapkan kepatuhan warga untuk mencapai tujuan pembangunan yang hanya berorientasi ekonomi dan menguntungkan segelintir golongan. Hal ini berdampak pada homogenisasi pola ekspresi budaya dari kelompok budaya dan kelas sosial yang beragam alih-alih membebaskan imajinasi. Kebijakan kebudayaan yang terpusat juga berdampak pada penyelenggaraan festival kebudayaan di daerah sebagai semata tontonan berdasarkan preferensi dari pusat yang mengebiri aspek-aspek emansipatif dan ekologis dari produksi seni berdasarkan kebutuhan dari daerah sendiri. Dapat disimpulkan bahwa kebijakan budaya yang terpusat tidak mendukung produksi kebudayaan yang sehat.
Melalui Undang-undang Pemajuan Kebudayaan, negara tidak lagi menguasai seluruh pelaksanaan produksi kebudayaan dari hulu ke hilir serta memonopoli interpretasinya. Negara “hanya” menjadi fasilitator dan katalisator yang secara efektif menyalurkan sumber-sumber daya agar dapat diakses secara adil dan proporsional oleh masyarakat seluas-luasnya dengan keberagaman suku, daerah, kelas sosial, kebutuhan dan seterusnya untuk produksi-produksi kebudayaan.
Penyelenggaraan festival pun demikian. Dengan menjadi fasilitator, negara dapat memberikan keleluasaan kepada pelaku-pelaku festival untuk mengembangkan model penyelenggaraannya, baik dalam mengumpulkan sumber daya melalui kerja-kerja penggalangan dana maupun berjejaring dengan festival-festival lain. Ciri khas dari penyelenggaran festival pasca UU Pemajuan Kebudayaan adalah pertukaran sumber daya antar festival sebagai perwujudan desentralisasi produksi kesenian. Secara organik festival-festival bertumbuh dengan saling mendukung satu sama lain yang mewujudkan sebuah ekosistem.
Uniknya situasi ini telah dilakukan oleh sejumlah festival yang berada di Indonesia Tengah dan Timur setidaknya selama lima tahun terakhir. Menyadari keterbatasan yang mereka hadapi, festival-festival ini berkolaborasi melalui pertukaran sumber daya pada setiap penyelenggaraan festival masing-masing. Hal ini diungkapkan oleh Eka Putra Nggalu, salah satu pendiri Komunitas Kahe di Maumere serta penggerak Flores Writers Festival. Pertukaran sumber daya ini misalnya adalah dukungan biaya perjalanan dan akomodasi untuk setiap narasumber yang berasal dari kota-kota penyelenggara festival ini. Festival-festival yang telah berekosistem ini antara lain Makassar International Writers Festival, Flores Writers Festival, Festival Sastra Banggai dan Festival Sastra Santarang. Mereka dikelola oleh komunitas-komunitas yang tumbuh secara organik selama dua dekade terakhir.
Pertukaran sumber daya ini juga berwujud pada pengembangan kapasitas para pelaku festival-festival itu. Mereka saling mengirim pelaku seni muda dari wilayah masing-masing untuk magang pada setiap penyelenggaraan festival-festival itu. Selain meningkatkan kecakapan tata kelola dan menjamin regenerasi, model ini juga makin mengakrabkan pelaku seni pada karakter geografis dan sosiokultural daerah masing-masing dan mitra. Model ini dapat mendorong akulturasi yang menjadi pelumas perkembangan kebudayaan dan wawasan untuk pengembangan festival-festival itu di masa depan. Imajinasi tentang Indonesia pun makin demokratis karena tidak hanya ditentukan secara terpusat. Dengan perspektif kewilayahan ini sorotan memang mengarah pada inisiatif tingkat lokal, karena menurut Maharani, tingkat kewilayahan akan lebih efektif dalam menggerakkan masyarakat dan mengolah pengetahuan lokal. Ia melanjutkan bahwa pengembangan masyarakat berbasis budaya melalui otonomi lokal akan lebih tepat sasaran (Investasi Kebudayaan untuk Masa Depan, dalam Dampak Seni di Masyarakat, Koalisi Seni Indonesia, 2018, hal. 7).
Ekosistem ini dirawat dengan hubungan yang setara dan tetap mengedepankan kebutuhan daerah masing-masing. Yang tidak kalah penting, dengan merawat ekosistem ini berarti mengurangi ketergantungan dari pusat yang berada di Jawa serta memupus potensi untuk terulangnya orientasi atau kepentingan dari pusat pada setiap penyelenggaraan festival budaya di daerah.
Negara sebagai fasilitator menunjukkan perannya dengan menyediakan akses langsung atas sumber daya untuk pelaku-pelaku seni di daerah. Model yang progresif ini dapat memupus pemusatan yang sebelumnya menempatkan elit-elit budaya di Jawa sebagai penginterpretasi tunggal atau gatekeeper atas pengembangan kebudayaan daerah. Padahal mereka sebetulnya kurang memahami isu dan konteks kedaerahan sehingga menggunakan standar yang Jawasentris saat menilai inisiatif-inisiatif kebudayaan di daerah. Melalui cara ini sumber daya jadi lebih merata diakses dan tidak hanya berputar di lingkaran yang terbatas; hanya dinikmati oleh beberapa kelompok kepentingan.
Pekerjaan rumah yang harus segera diselesaikan adalah menyelaraskan nomenklatur kebudayaan pada pranata-pranata kebudayaan di daerah yang acapkali masih menempel pada nomenklatur pariwisata. Hal ini menjadikan pengembangan festival di daerah banyak dibebani oleh variabel-variabel ekonomi turisme, ketimbang variabel-variabel kebudayaannya. Selain itu prinsip keterbukaan dan transparansi pada pelaksanaan pemajuan kebudayaan melalui platform Dana Indonesia seringkali masih tidak bisa diikuti oleh pranata-pranata negara di daerah yang justru terus merawat struktur vertikal dan birokratis yang tidak membebaskan.
Ekosistem yang telah dirawat oleh festival-festival itu perlahan membentuk nilai-nilai kewargaan yang baru yang dibangun atas hubungan yang saling menguntungkan dan setara. Diharapkan model ekosistem ini dapat menular ke daerah-daerah lain. Dengan demikian situasi ini sekali lagi menunjukkan dampak baik pelaksanaan Pemajuan Kebudayaan yang dapat mendorong kebebasan manusia dalam memaknai diri, perubahan sosial dan lingkungan melalui kesenian. Dalam hal ini berarti negara dapat menunaikan tugasnya dalam mencerdaskan kehidupan bangsa.
*Penulis: Chabib Duta Hapsoro, kurator seni rupa dan kandidat doktor di National University of Singapore