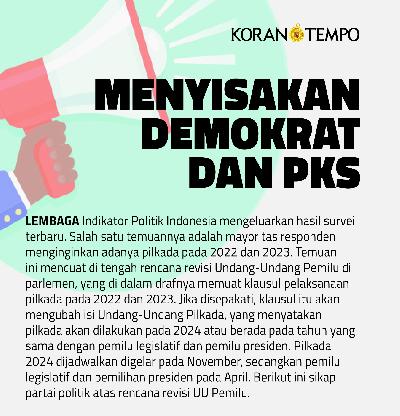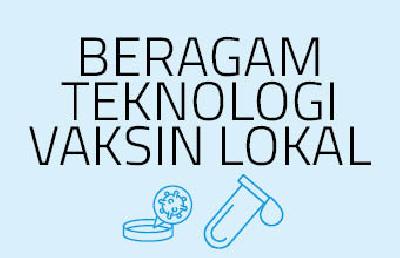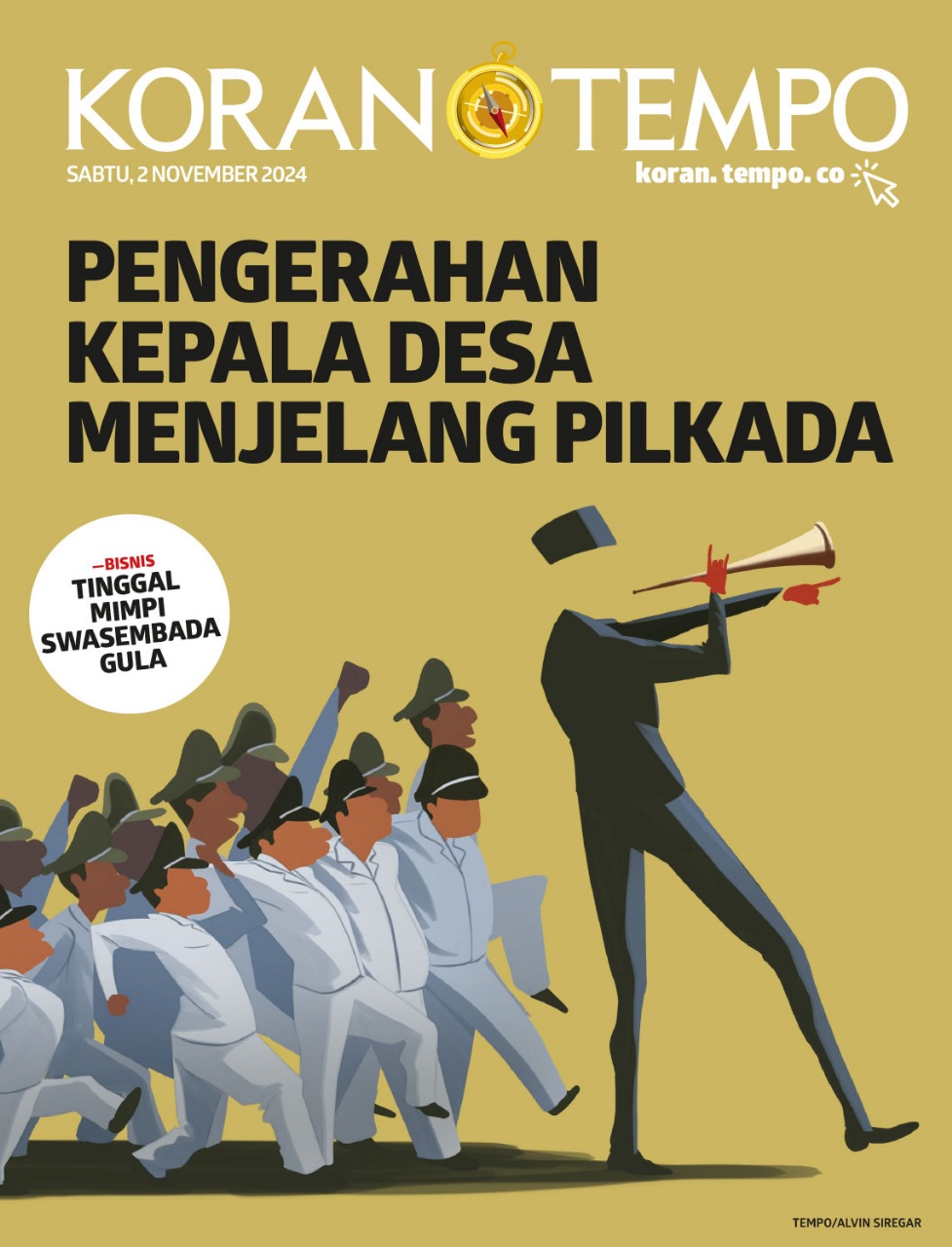Kekerasan di Ruang Tahanan
arsip tempo : 173057199836.

Polisi harus mengakhiri segala bentuk kekerasan terhadap saksi ataupun tersangka dalam pemeriksaan. Untuk mendapatkan pengakuan, petugas tidak boleh memaksa, mengancam, apalagi menyiksa seseorang—betapa pun orang itu terindikasi melakukan kejahatan.
Tewasnya Herman, tersangka pencuri telepon seluler, di tahanan Kepolisian Resor Kota Balikpapan, Kalimantan Timur, membuktikan bahwa praktik penyiksaan oleh polisi masih terjadi. Herman, yang d
...
Berlangganan untuk lanjutkan membaca.
Kami mengemas berita, dengan cerita.
 Manfaat berlangganan Tempo Digital? Lihat Disini
Manfaat berlangganan Tempo Digital? Lihat Disini