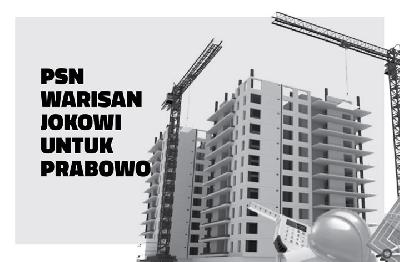Apa Boleh Spill Identitas Pelaku Kekerasan Seksual di Media Sosial?
Bolehkah korban kekerasan seksual mengungkap identitas terduga pelaku di media sosial?
arsip tempo : 173041742497.

HALO pengasuh Klinik Hukum bagi Perempuan. Perkenalkan, saya Rebeca. Saya sering membaca di media sosial seperti X (Twitter) soal korban yang spill (mengungkap) kasus kekerasan seksual yang dialaminya. Ada yang menceritakan kasusnya dengan menyamarkan identitas terduga pelaku, tapi ada juga yang mengungkap secara jelas identitas terduga pelaku. Pertanyaan saya, mengapa sekarang ini banyak korban yang spill kasus pelecehan seksual yang ia alami di media sosial? Apakah ada konsekuensi hukumnya apabila mengungkap identitas terduga pelaku pelecehan seksual di medsos? Sebab, saya sering mendengar dan membaca berita soal korban atau si pengungkap identitas terduga pelaku pelecehan seksual yang malah dilaporkan ke polisi dengan kasus pencemaran nama atau fitnah. Mohon penjelasannya.
Terima kasih.
Rebeca, Yogyakarta
Jawaban:
Terima kasih Rebeca sudah menghubungi Klinik Hukum bagi Perempuan.
Mengenai pertanyaan mengapa sekarang banyak korban yang spill kasus pelecehan seksual yang ia alami di media sosial, mungkin ada beberapa alasan. Pertama, media sosial mampu memberikan suara kepada para penyintas (korban) yang merasa sulit mendapatkan keadilan hukum, misalnya sudah melaporkan kasusnya ke institusi tertentu (seperti tempat pelaku bekerja, kampus, dan lain-lain) tapi tidak ada dukungan dan penyelesaiannya, atau sudah melapor ke polisi tapi prosesnya tersendat.
Kedua, korban ingin pelaku mendapatkan sanksi sosial dan meminta maaf secara terbuka. Ketiga, pelaku adalah tokoh atau pejabat negara yang sulit dijangkau hukum, sehingga korban yakin kasusnya harus diviralkan agar ada proses hukum yang dapat memberikan keadilan kepada korban (no viral, no justice).
Spill atau mengungkap kekerasan seksual yang dialami melalui media sosial (speak up), di banyak negara, menjadi salah satu upaya atau cara agar perempuan korban kekerasan seksual mendapatkan keadilan. Salah satunya melalui gerakan Me Too yang sekarang sangat terkenal dan mampu membawa perempuan menerobos keadilan.
Gerakan ini berawal dari individu-individu korban kekerasan seksual yang berani bicara lalu menjadi gerakan bersama. Bahkan, di Amerika Serikat misalnya, gerakan Me Too yang awalnya berfokus kepada pelaku kejahatan individu, sekarang berkembang menjadi gerakan advokasi. Tujuannya untuk mengubah sistem peradilan pidana dan perdata dengan mengusulkan rancangan undang-undang yang berupaya menghilangkan hambatan bagi para korban dalam menyelesaikan kasus kekerasan seksual, baik itu dalam sistem peradilan pidana bagi korban yang ingin menyelesaikannya secara pidana maupun sistem peradilan perdata, bagi korban yang ingin menyelesaikannya secara keperdataan (ganti rugi materiil).
Di Indonesia, kita sudah memiliki Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) yang diatur secara khusus (lex specialis). Perlu dicatat, melalui UU TPKS, korban akan mendapat keadilan hukum sekaligus ganti rugi materiil (restitusi) melalui sistem peradilan pidana.
Kembali ke permasalahan spill/speak up, kami menyimpulkan apa yang dilakukan oleh banyak korban kekerasan seksual di media sosial patut kita apresiasi. Itu merupakan suatu keberanian yang luar biasa untuk dapat mengungkap kekerasan seksual yang dialami agar pelaku mendapat sanksi hukum dan sosial atas perbuatannya. Karena itu, bagi kami, spill/speak up sangatlah penting, bahkan seharusnya menjadi gerakan bersama-sama agar UU TPKS dapat segera diimplementasikan.
Konsekuensi hukum jika mengungkap identitas terduga pelaku kekerasan seksual di media sosial
Pertama-tama, perlu kami jelaskan bahwa kekerasan seksual merupakan tindak pidana murni yang diatur secara khusus melalui UU TPKS. Karena itu, pemeriksaan untuk membuktikan pelaku secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana kekerasan seksual hanyalah melalui putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap. Dengan demikian, mengungkap identitas terduga pelaku kekerasan seksual di media sosial berpotensi menimbulkan permasalahan hukum apabila belum ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atau minimal sedang dalam proses hukum di tingkat kepolisian sebagai berikut:
1. Melanggar asas praduga tak bersalah
Asas praduga tak bersalah diatur dalam Pasal 8 ayat 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (UU Kekuasaan Kehakiman) yang berbunyi sebagai berikut: “Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, atau dihadapkan di depan pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sebelum ada putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap.”
2. Pencemaran nama
Perbuatan pencemaran nama diatur dalam Pasal 27A Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) sebagai berikut: “Setiap orang dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik orang lain dengan cara menuduhkan suatu hal, dengan maksud supaya hal tersebut diketahui umum dalam bentuk Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang dilakukan melalui Sistem Elektronik.”
Tindak pidana dalam Pasal 27A UU ITE ini adalah tindak pidana aduan. Artinya, aparat penegak hukum hanya bisa memproses tindak pidana ini jika ada korban atau orang yang merasa dicemarkan namanya, bukan badan hukum.
Namun perlu diketahui bahwa perbuatan pencemaran nama sebagaimana diatur dalam Pasal 27A UU ITE tidak dapat dipidana jika dilakukan untuk kepentingan umum atau jika dilakukan karena terpaksa membela diri. Misalnya, korban atau pendamping korban sudah melaporkan kasus kekerasan seksual tersebut kepada aparat penegak hukum (polisi), tapi proses hukumnya tidak berjalan atau pelaporan sudah dalam tahap penyidikan dan pelaku sudah ditetapkan sebagai tersangka tapi tak dilakukan penahanan. Lalu, ketika kasusnya diviralkan di medsos, pihak kepolisian memprosesnya. Kasus-kasus no viral, no justice seperti ini banyak terjadi pada perempuan, seperti pada kasus-kasus KDRT dan kekerasan seksual.
3. Melanggar pelindungan data pribadi
Mengungkap identitas terduga pelaku pelecehan seksual juga berpotensi melanggar ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP). Misalnya, di medsos diungkap nama lengkap, tempatnya bekerja, atau informasi lain yang termasuk data pribadi bersifat umum sebagaimana diatur dalam UU PDP.
Berdasarkan uraian di atas, dapat kami simpulkan bahwa spill/speak up atas kasus kekerasan seksual di media sosial yang tidak berpotensi menimbulkan permasalahan hukum adalah sebagai berikut:
a. Spill/speak up atas kasus kekerasan seksual tanpa menyebutkan identitas lengkap atau informasi yang berkaitan dengan data pribadi, kecuali sudah ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atau minimal sedang dalam proses hukum di tingkat kepolisian atau diberitakan media.
b. Terminologi yang digunakan dalam penyebutan nama pelaku apabila proses hukum masih berjalan harus menggunakan “terduga” di depan nama pelaku tindak pidana kekerasan seksual. Apabila sudah ditetapkan sebagai tersangka, terminologi yang digunakan di depan nama pelaku adalah “tersangka”, dan jika sudah ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, digunakan terminologi “terpidana” di depan nama pelaku.
c. Spill/speak up kasus kekerasan seksual untuk kasus-kasus yang sudah diberitakan media dapat dilakukan sebagai gerakan speak up sehingga menjadi perhatian aparat penegak hukum bahwa proses hukum yang sedang diselesaikannya dipantau oleh masyarakat hingga korban mendapatkan keadilan. Tindakan itu juga dapat menjadi gerakan untuk mendorong aparat penegak hukum, khususnya polisi, agar mengkonstruksi kasusnya menggunakan UU TPKS, walaupun belum ada peraturan turunan yang mengatur teknis penerapannya. Mengingat hukum acara khusus diatur secara materiil dalam UU TPKS, penegak hukum dapat menerjemahkannya secara formil. Artinya, menggunakan hukum acara pidana umum dengan memasukkan syarat-syarat khusus yang berkaitan dengan formil penegakan UU TPKS
Demikian penjelasan dari kami. Semoga bermanfaat sebagai tambahan informasi bagi korban dan masyarakat secara umum dalam mengungkap visibilitas tindak pidana kekerasan seksual yang harus dicegah dan dihentikan, serta terpenuhinya akses keadilan bagi korban melalui penegakan UU TPKS.
Sri Agustini
Advokat Probono LBH APIK Jakarta