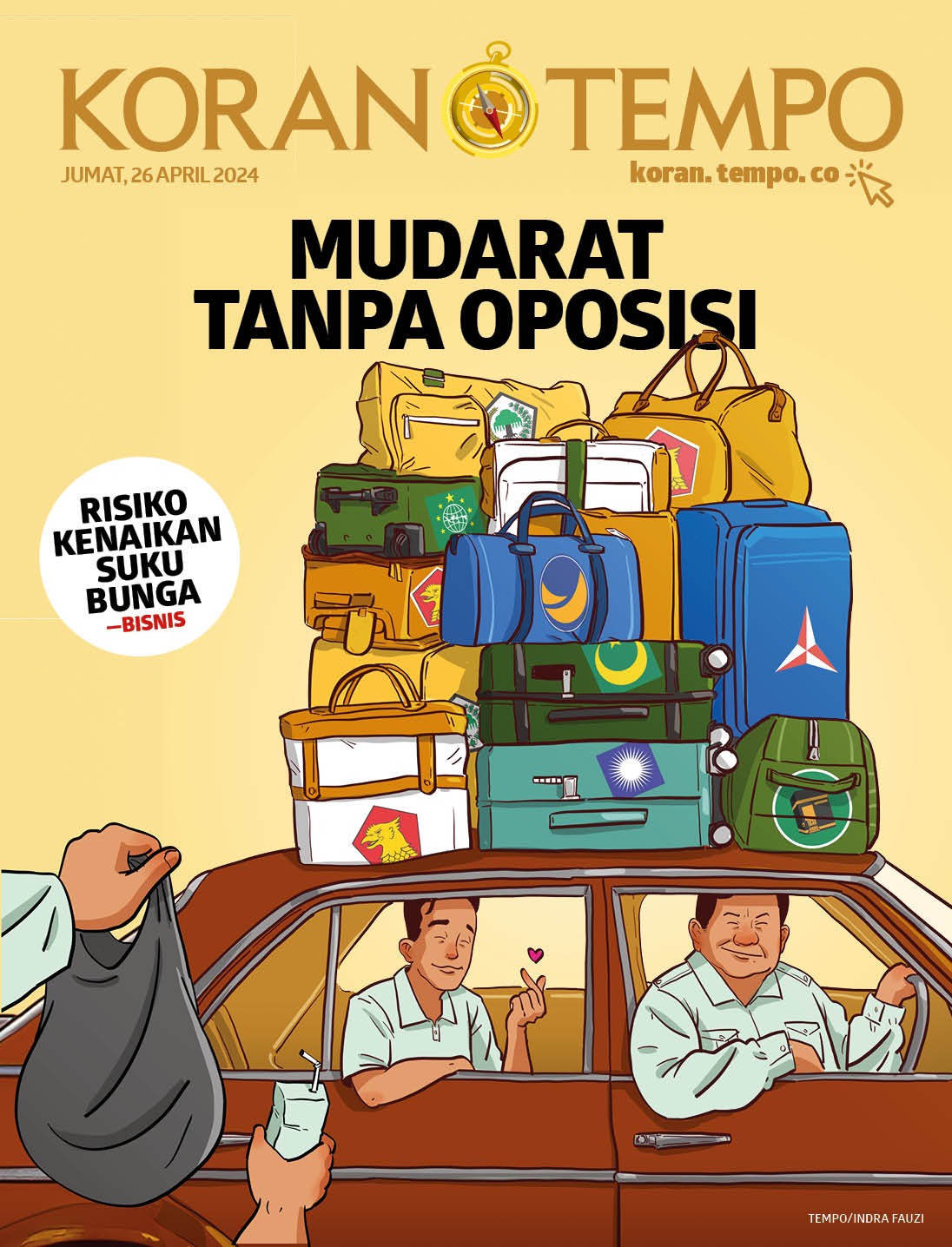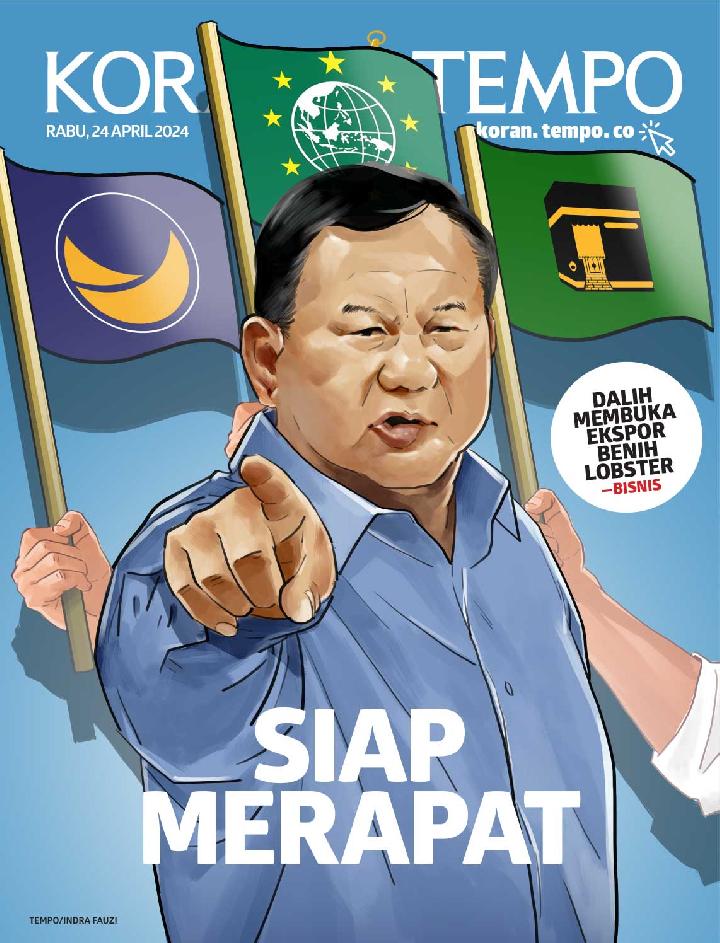Di Balik Pintu Surga Persia
arsip tempo : 171411538184.

Saya tiba di depan hotel itu pada subuh. Saya bergegas menuju medan Imam, plaza di pusat Kota Isfahan, Iran, yang berdiri sejak abad ke-17. Matahari pada pekan kedua Januari lalu masih enggan membagi seluruh sinarnya. Tapi biasanya sudah cukup untuk membangunkan kawanan gagak yang ramai menyambut saya dan beberapa peneliti Indonesia di langit pagi itu.
Letih sisa perjalanan naik pesawat dari Teheran, ibu kota Iran, tidak saya hiraukan. Dengan ra
...
Berlangganan untuk lanjutkan membaca.
Kami mengemas berita, dengan cerita.
 Manfaat berlangganan Tempo Digital? Lihat Disini
Manfaat berlangganan Tempo Digital? Lihat Disini