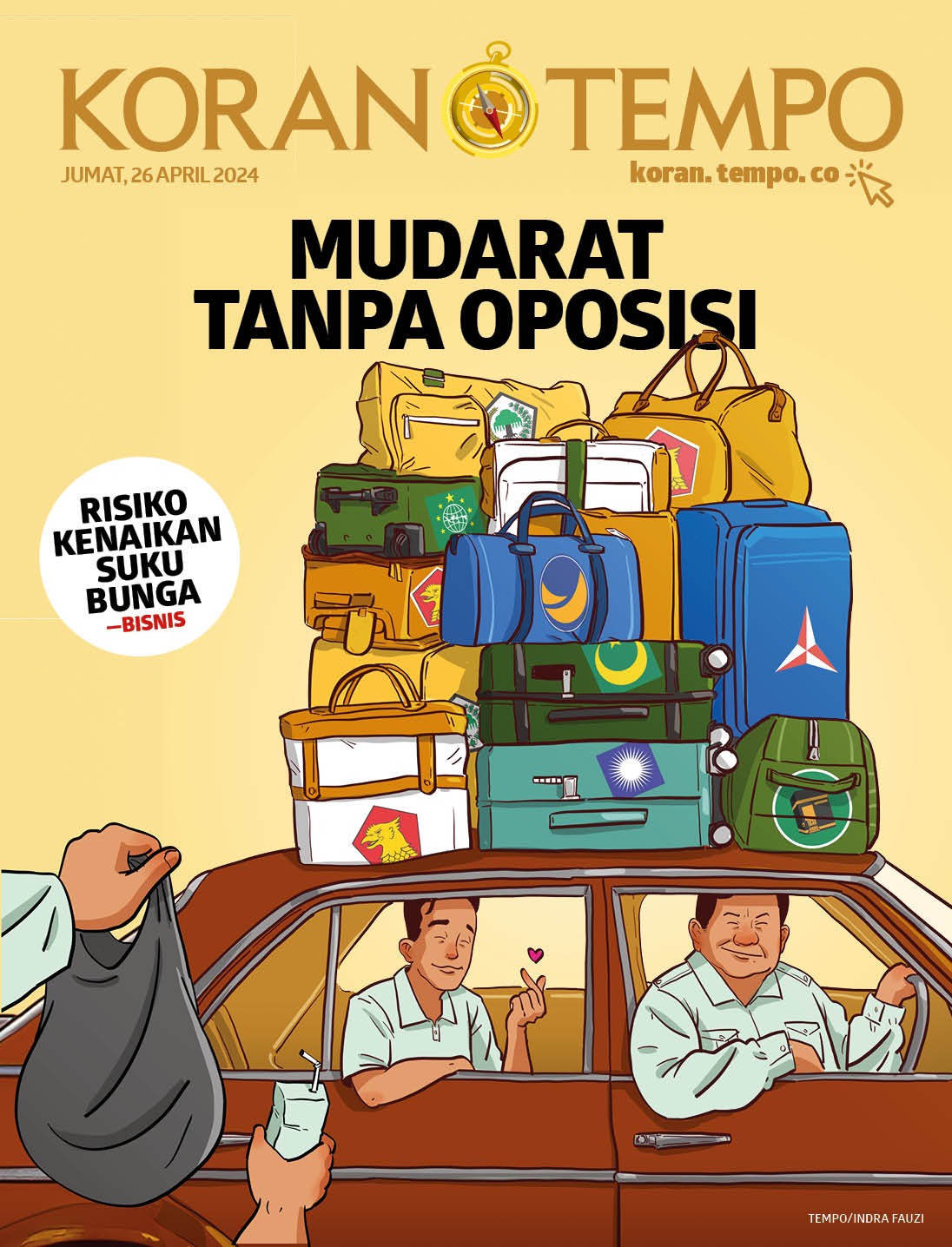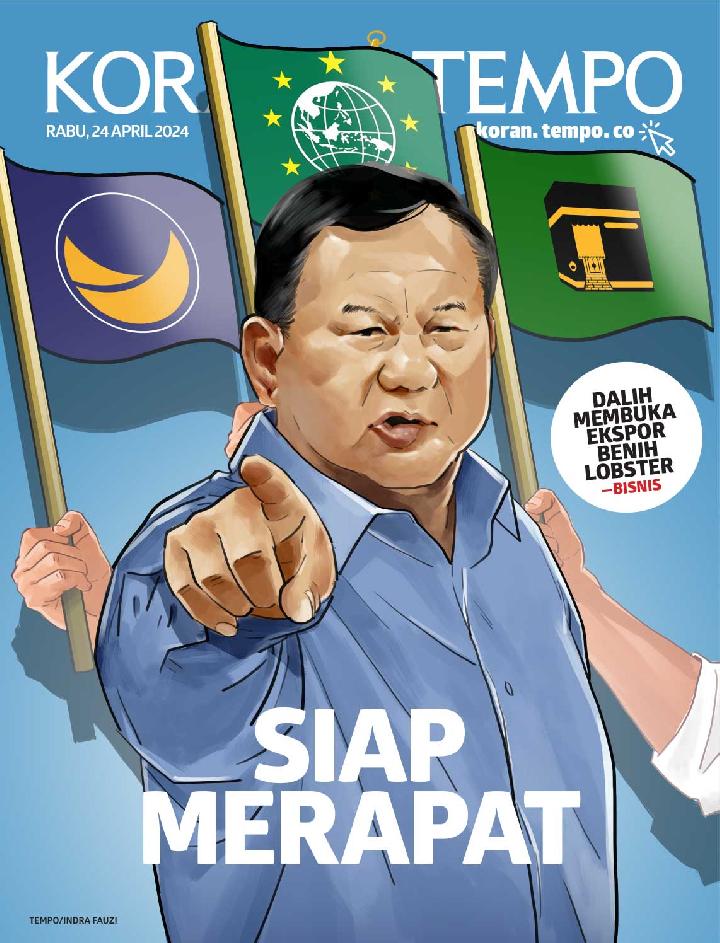Perubahan Iklim dan Potensi Hutan Indonesia
arsip tempo : 1714118344100.

Fachruddin M. Mangunjaya, PENCINTA LINGKUNGAN
Perubahan iklim telah menjadi fakta yang mengkhawatirkan. Panel Antarpemerintah dalam Perubahan Iklim merilis laporannya pada 2 Februari ini. Laporan itu mensinyalir perubahan iklim lebih mencemaskan daripada dugaan semula. Di Indonesia, gejala perubahan iklim dirasakan akibat pergeseran musim yang ekstrem dari musim kemarau menjadi musim hujan yang kita alami pada beberapa tahun terakhir ini. Atau per
...
Berlangganan untuk lanjutkan membaca.
Kami mengemas berita, dengan cerita.
 Manfaat berlangganan Tempo Digital? Lihat Disini
Manfaat berlangganan Tempo Digital? Lihat Disini