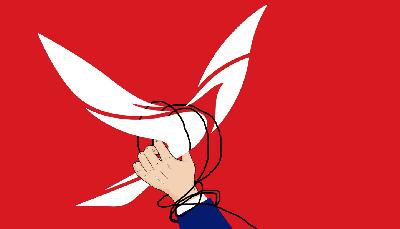Bagaimana Perbedaan Penanganan Kasus Kekerasan Seksual yang Pelakunya Anak dan Orang Dewasa?
Tindak pidana kekerasan seksual yang dilakukan oleh anak dan orang dewasa harus ditangani secara berbeda.
arsip tempo : 172676456819.

Halo, saya Kayla. Saya prihatin soal banyaknya kasus kekerasan seksual yang makin marak belakangan ini. Ada kasus pelaku masih berusia anak memperkosa dan menganiaya korban hingga meninggal. Ada juga kasus pekerja rumah tangga yang masih di bawah umur diperkosa oleh majikan dan sudah dilaporkan ke polisi, tapi malah diupayakan perdamaian antara pelaku dan korban melalui mediasi. Sebenarnya bagaimana penanganan kasus pemerkosaan bagi pelaku anak dan orang dewasa?
Jawaban:
Halo, Kayla. Terima kasih telah berkonsultasi dengan Klinik Hukum Perempuan. Kami turut prihatin atas kekerasan seksual yang terjadi pada korban. Menjawab pertanyaan tersebut, kami akan mengulas sedikit kedua kasus yang dimaksudkan.
Kasus pertama, seorang anak perempuan mengalami pemerkosaan dan penganiayaan hingga meninggal. Pelakunya adalah MZ, 13 tahun, NS (12), AS (12), dan IS (16). Dari keempat pelaku, hanya IS yang ditahan, sementara tiga pelaku lainnya tidak ditahan. Perbedaan penahanan inilah yang menimbulkan pro-kontra. Masyarakat menuntut pertanggungjawaban para pelaku, bahkan sampai menginginkan perubahan usia pertanggungjawaban pidana anak dalam sistem peradilan pidana anak (SPPA) karena tidak memberikan keadilan kepada korban dan keluarganya. Selain itu, masyarakat khawatir tidak ada efek jera bagi para pelaku.
Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak
Kita mulai dengan memahami apa sebenarnya SPPA. SPPA adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum, dari tahap penyelidikan sampai tahap pembimbingan setelah menjalani pidana sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA).
Kemudian siapa saja yang termasuk kategori anak yang berhadapan dengan hukum? Anak yang berhadapan dengan hukum dibagi menjadi tiga kategori. Pasal 1 angka 2 UU SPPA menyebutkan anak berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana. Penjelasan lebih lanjut sebagai berikut ini.
Pasal 1 angka 3 UU SPPA menyebutkan anak yang berkonflik dengan hukum, selanjutnya disebut anak, adalah anak yang telah berumur 12 tahun, tapi belum berumur 18 tahun, yang diduga melakukan tindak pidana.
Pasal 1 angka 4 UU SPPA menyatakan anak yang menjadi korban tindak pidana, yang selanjutnya disebut dengan anak korban, adalah anak yang belum berumur 18 tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana.
Sementara itu, anak yang menjadi saksi tindak pidana, yang selanjutnya disebut anak saksi, adalah anak yang belum berumur 18 tahun yang dapat memberikan keterangan untuk kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan dalam sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat, dan/atau dialaminya sendiri.
Dalam mekanisme SPPA wajib mengutamakan pendekatan keadilan restoratif dan wajib diupayakan diversi sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 5 UU SPPA. Apa yang dimaksud diversi dalam sistem peradilan pidana anak?
Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Hal itu dijelaskan dalam Pasal 1 angka 7 UU SPPA. Pasal 6 UU SPPA menjelaskan, diversi bertujuan mencapai perdamaian antara korban dan anak, menyelesaikan perkara anak di luar proses peradilan, menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan, mendorong masyarakat berpartisipasi, serta menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak.
Tapi tunggu dulu, jangan terburu-buru geram saat membaca kata “perdamaian” yang menjadi salah satu tujuan diversi, karena mekanisme diversi belum selesai disini. Mari kita lanjutkan dulu pemahaman tentang diversi lebih lanjut!
Pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara anak di pengadilan negeri wajib diupayakan diversi. Pasal 7 UU SPPA menyatakan diversi dilaksanakan jika tindak pidana yang dilakukan diancam dengan pidana di bawah 7 tahun penjara dan bukan pengulangan tindak pidana.
Diversi Wajib Memperhatikan Kepentingan Korban
Proses diversi juga wajib memperhatikan kepentingan korban, kesejahteraan dan tanggung jawab anak, penghindaran stigma negatif, penghindaran pembalasan, keharmonisan masyarakat, kepatutan, kesusilaan, serta ketertiban umum (Pasal 8 UU SPPA). Proses diversi dilakukan melalui musyawarah dengan melibatkan anak dan orang tua atau walinya, korban dan/atau orang tua/walinya, pembimbing kemasyarakatan, serta pekerja sosial profesional berdasarkan pendekatan keadilan restoratif. Apabila diperlukan, proses diversi dapat melibatkan tenaga kesejahteraan sosial dan/atau masyarakat.
Penyidik, penuntut umum, dan hakim dalam melakukan diversi harus mempertimbangkan kategori tindak pidana, umur anak, hasil penelitian kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan, serta dukungan lingkungan keluarga dan masyarakat (Pasal 9 UU SPPA). Kesepakatan diversi harus mendapatkan persetujuan korban dan/atau keluarga anak korban serta kesediaan anak dan keluarganya, kecuali untuk tindak pidana yang berupa pelanggaran, tindak pidana ringan, tindak pidana tanpa korban, atau nilai kerugian korban tidak lebih dari nilai upah minimum provinsi setempat (Pasal 9 ayat 2 UU SPPA).
Hasil kesepakatan diversi antara lain dapat berbentuk perdamaian dengan atau tanpa ganti kerugian, penyerahan kembali kepada orang tua/wali, keikutsertaan dalam pendidikan atau pelatihan di lembaga pendidikan atau LPKS paling lama tiga bulan, atau pelayanan masyarakat (Pasal 11 UU SPPA). Proses peradilan pidana anak dilanjutkan apabila proses diversi tidak menghasilkan kesepakatan atau kesepakatan diversi tak dilaksanakan (Pasal 13 UU SPPA).
Pembatasan Syarat Usia Penahanan terhadap Anak Berkonflik dengan Hukum
Sebelum dan setelah dilakukan diversi, penahanan terhadap anak hanya dapat dilakukan dengan syarat anak telah berumur 14 tahun atau lebih serta diduga melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana 7 tahun penjara atau lebih (Pasal 32 ayat 2 UU SPPA). Khusus mengenai sanksi terhadap anak ditentukan berdasarkan perbedaan umur anak, yaitu bagi anak yang masih berumur kurang dari 12 tahun hanya dikenai tindakan, sedangkan bagi anak yang telah mencapai umur 12-18 tahun dapat dijatuhi tindakan dan pidana.
Pendekatan Keadilan Restoratif dan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak
Setelah memahami diversi, anak perlu mendapat pelindungan dari dampak negatif perkembangan pembangunan yang cepat, arus globalisasi di bidang komunikasi dan informasi, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta perubahan gaya dan cara hidup sebagian orang tua yang telah membawa perubahan sosial yang mendasar dalam kehidupan masyarakat yang sangat berpengaruh terhadap nilai dan perilaku anak. Penyimpangan tingkah laku atau perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh anak, antara lain, disebabkan oleh faktor di luar diri anak tersebut.
Substansi paling mendasar dalam UU SPPA adalah pengaturan secara tegas mengenai keadilan restoratif dan diversi yang dimaksudkan untuk menghindari serta menjauhkan anak dari proses peradilan sehingga dapat menghindari stigmatisasi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Anak juga diharapkan dapat kembali ke lingkungan sosial secara wajar.
Karena itu, sangat diperlukan peran serta semua pihak dalam rangka mewujudkan hal tersebut. Proses itu harus bertujuan terciptanya keadilan restoratif, baik bagi anak maupun bagi korban. Keadilan restoratif merupakan suatu proses diversi, yaitu semua pihak yang terlibat dalam suatu tindak pidana tertentu bersama-sama mengatasi masalah serta menciptakan suatu kewajiban untuk membuat segala sesuatu menjadi lebih baik dengan melibatkan korban, anak, ataupun masyarakat dalam mencari solusi guna memperbaiki, rekonsiliasi, yang tidak berdasarkan pembalasan.
Tidak berdasarkan pembalasan adalah hal penting bagi anak berkonflik dengan hukum dalam sistem peradilan pidana anak. Mengapa demikian? Narasi penghukuman atau pembalasan sering kali tidak sejalan dengan efektivitas penjara dalam mendukung pembinaan anak berkonflik dengan hukum. Selain itu, pemerintah dan masyarakat perlu melihat lebih dalam faktor penyebab anak terpapar pornografi hingga melakukan tindak pidana kekerasan seksual, dimulai dari pola pengasuhan dan dinamika keluarga serta lingkungan sosial sehari-hari.
Salah Paham Keadilan Restoratif
Lanjut pada kasus kedua yang Kayla sampaikan dalam pertanyaan, pekerja rumah tangga anak mengalami kekerasan seksual, yang pelakunya adalah pemberi kerja. Kasus ini juga sudah dilaporkan kepada pihak kepolisian. Namun pelaku mengajukan permohonan penyelesaian melalui mekanisme keadilan restoratif. Benarkah tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak dapat diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif?
Keadilan restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan bukan pembalasan sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 3 Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif (Perpol Nomor 8/2021). Sebenarnya, definisi keadilan restoratif dalam Perpol Nomor 8/2021 sama dengan definisi keadilan restoratif dalam UU SPPA. Namun penerapannya berbeda dalam kedua kasus tersebut.
Prinsip keadilan restoratif dalam penanganan tindak pidana sering disalahartikan dan disederhanakan sebagai upaya perdamaian antara pelaku dan korban untuk menghentikan proses pidana. Pasal 23 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) secara tegas mengatur bahwa tindak pidana kekerasan seksual tidak dapat diselesaikan di luar proses peradilan, kecuali terhadap pelaku anak. Seperti yang telah dijelaskan di atas, terhadap pelaku anak, pendekatan keadilan restoratif dilakukan melalui mekanisme diversi.
Tindakan kepolisian mengupayakan keadilan restoratif berdasarkan Perpol Nomor 8/2021 pada kasus ini bertentangan dengan aturan yang lebih tinggi (lex superior) dan khusus (lex specialis), yaitu UU TPKS dan UU Perlindungan Anak. Polisi gagal memahami pengaturan penanganan kekerasan seksual dan menunjukkan keberpihakan kepada korban, apalagi korban merupakan anak di bawah umur yang secara aturan dilindungi berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Anak serta Konvensi Hak Anak. Karena itu, pada kesempatan pertama, seharusnya permohonan keadilan restoratif itu ditolak dan batal demi hukum.
Sekali lagi, penting bagi aparat penegak hukum memahami karakteristik tindak pidana kekerasan seksual sehingga mampu menghadirkan penanganan yang berperspektif korban.
Demikian penjelasan kami.
Tutut Tarida
Kolektif Advokat untuk Keadilan Gender