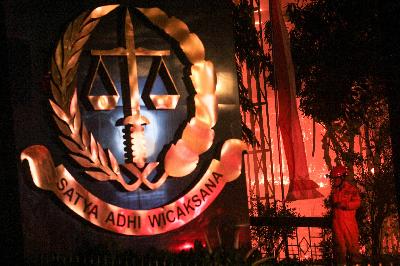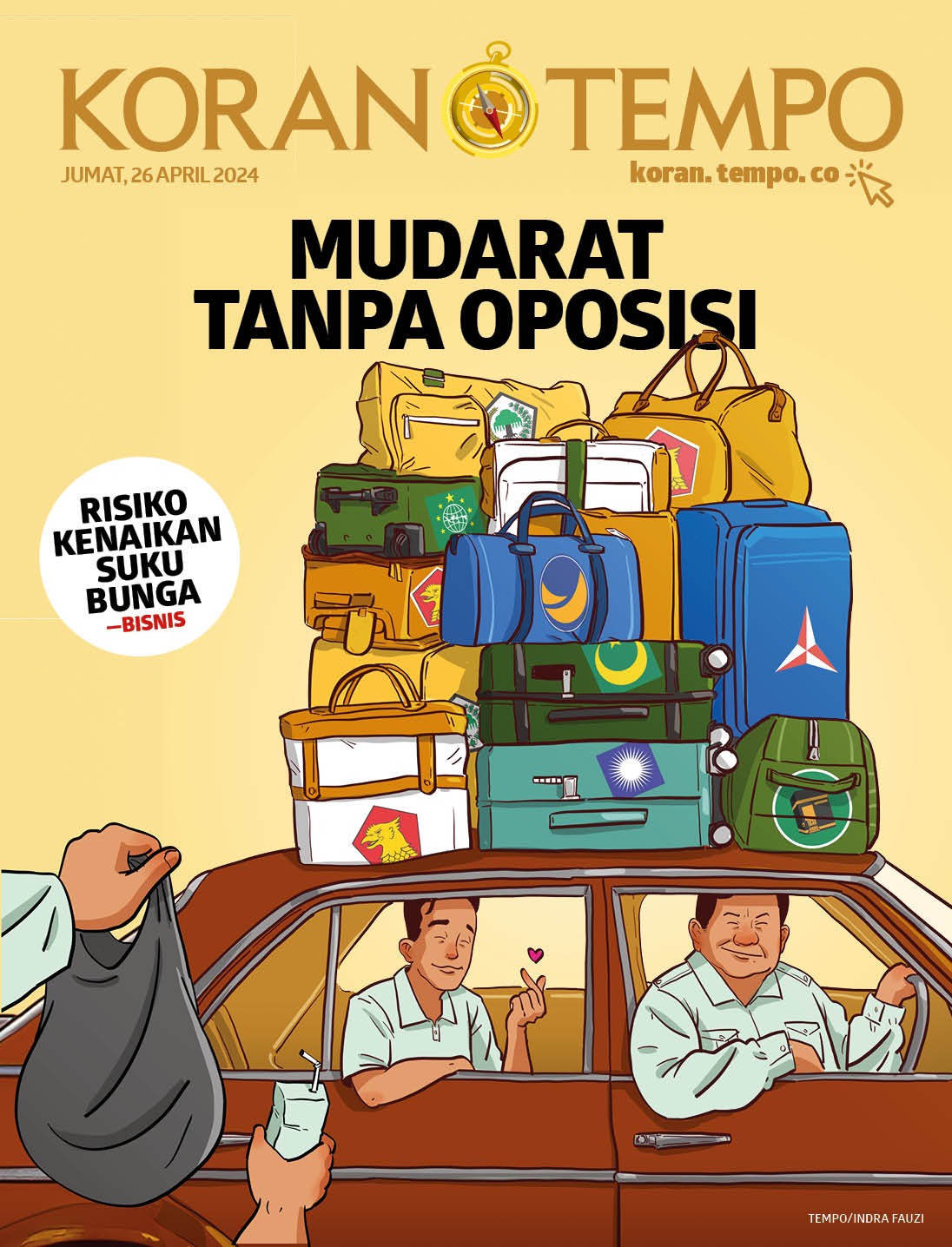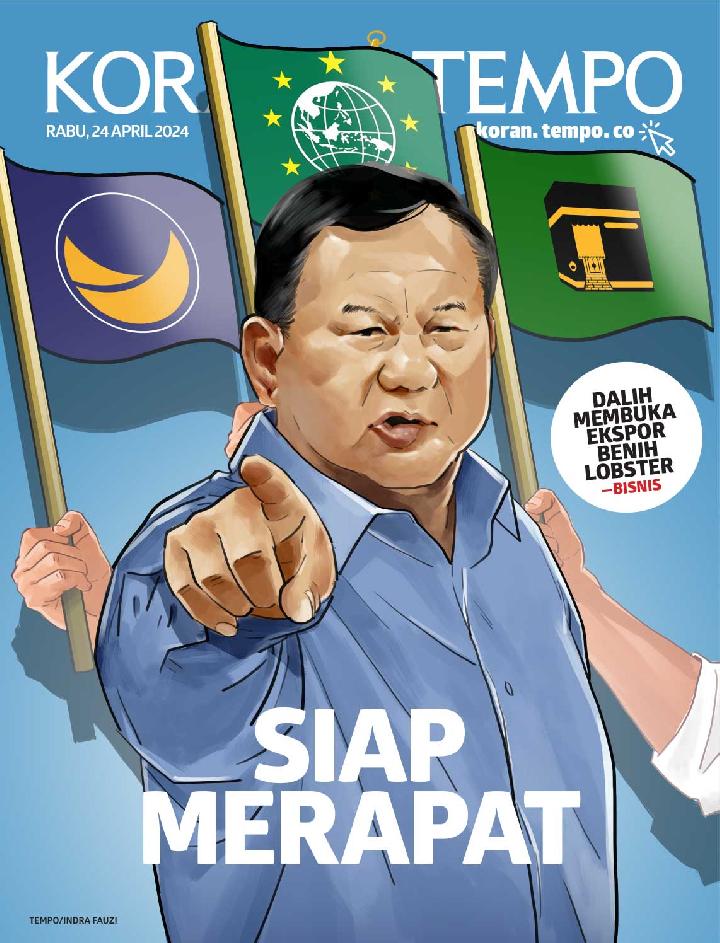Transparansi Anggaran Influencer
arsip tempo : 171414854996.

Pemerintah sudah seharusnya menjelaskan alasan dan manfaat penggunaan dana Rp 90,45 miliar untuk membayar pemengaruh alias influencer di media sosial. Jejak anggaran itu ditemukan tim Indonesia Corruption Watch belum lama ini.
Tim ICW menelusuri pengadaan barang dan jasa berkaitan dengan aktivitas digital 41 instansi pemerintah pusat sejak 2014 hingga 2020. Temuannya, nilai total anggaran untuk aktivitas digital pemerintah sekitar R...

Berlangganan untuk lanjutkan membaca.
Kami mengemas berita, dengan cerita.
 Manfaat berlangganan Tempo Digital? Lihat Disini
Manfaat berlangganan Tempo Digital? Lihat Disini