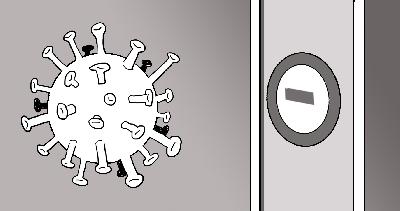Menggelorakan Komitmen Jassin
arsip tempo : 171400423725.

Ia telah berpulang dua dekade lalu. H.B. Jassin lahir pada 31 Juli 1917 dan wafat pada 11 Maret 2000. Pemikiran dan karya-karyanya masih terus hidup dan tetap menjadi acuan dalam dunia sastra. Pada 11 Maret lalu, Pusat Dokumentasi Sastra (PDS) H.B. Jassin menggelar acara untuk mengenang kritikus dan dokumentator ini. Sehari kemudian, 12 Maret, Bentara Budaya menggelar kegiatan serupa. Dari dua acara tersebut, menguat gagasan akan pentingnya langk
...
Berlangganan untuk lanjutkan membaca.
Kami mengemas berita, dengan cerita.
 Manfaat berlangganan Tempo Digital? Lihat Disini
Manfaat berlangganan Tempo Digital? Lihat Disini