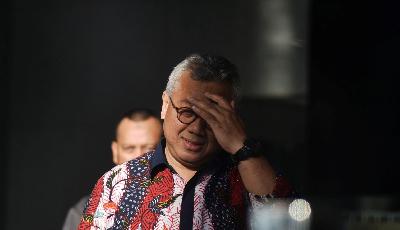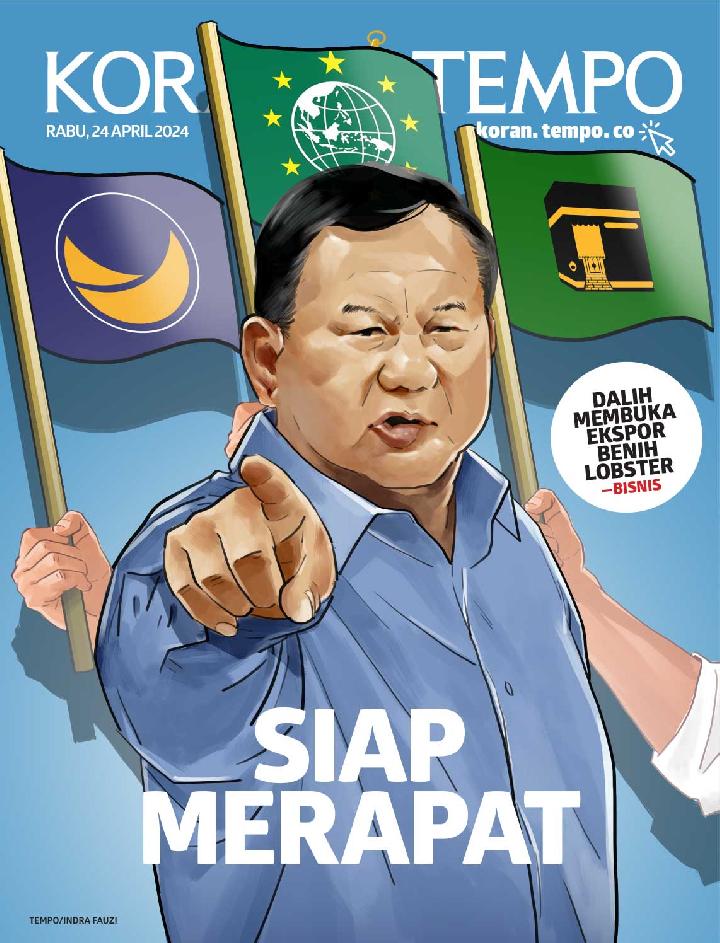Agenda Pemberantasan Korupsi bagi Kapolri Baru
arsip tempo : 171403834586.
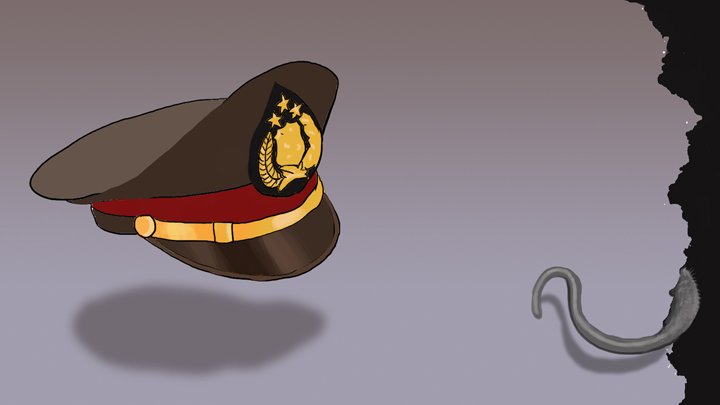
Kurnia Ramadhana
Peneliti Hukum Indonesia Corruption Watch
Teka-teki perihal siapa perwira tinggi Kepolisian Republik Indonesia yang akan menggantikan Jenderal Idham Azis sebagai Kepala Polri akhirnya terjawab. Presiden Joko Widodo menunjuk Komisaris Jenderal Listyo Sigit Prabowo sebagai calon tunggal pemimpin Korps Bhayangkara. Segudang pekerjaan rumah Kapolri baru pun telah menanti. Salah satunya menyoal agenda pemberantasan korupsi.
Meskipu
...
Berlangganan untuk lanjutkan membaca.
Kami mengemas berita, dengan cerita.
 Manfaat berlangganan Tempo Digital? Lihat Disini
Manfaat berlangganan Tempo Digital? Lihat Disini