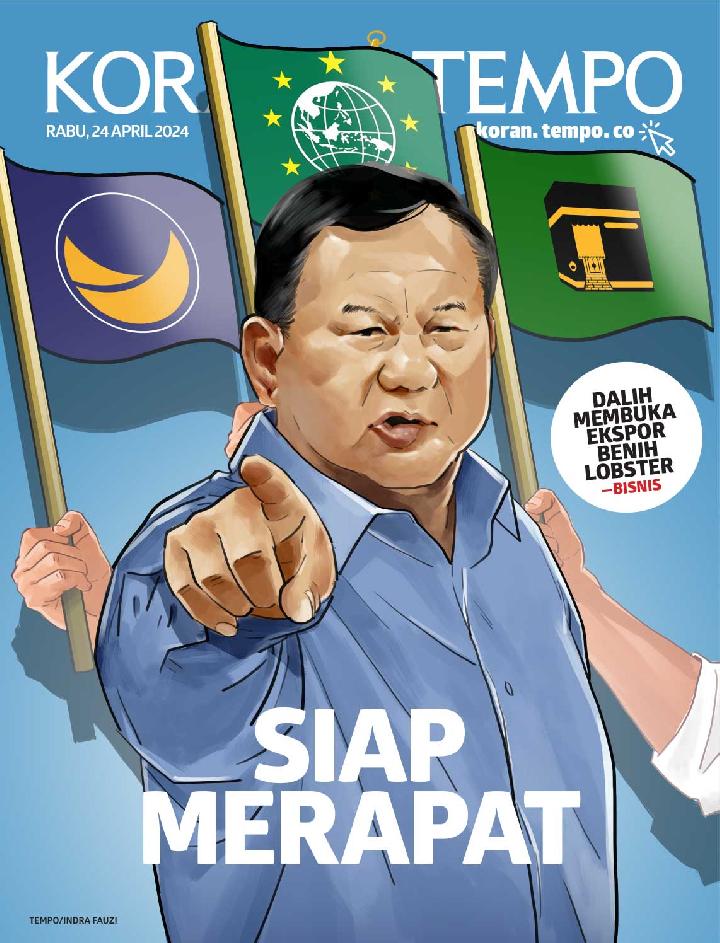Gagap Gejolak Cabai
Gonjang-ganjing harga cabai selalu berulang tiap tahun. Perlu intervensi pemerintah.
arsip tempo : 171405398857.

Jojo
Kandidat Doktor Ilmu Ekonomi Pertanian IPB
Cabai begitu populer di kalangan masyarakat Indonesia yang suka rasa pedas. Bahkan angka kebutuhan cabai segar di tingkat rumah tangga hampir 61 persen dan sisanya untuk industri. Hal tersebut menunjukkan bagaimana kecenderungan masyarakat yang senang mengkonsumsi cabai segar dibandingkan dengan yang sudah diolah. Gejolak harga cabai ikut mempengaruhi perekonomian nasional. Hal ini terlihat dari n...

Berlangganan untuk lanjutkan membaca.
Kami mengemas berita, dengan cerita.
 Manfaat berlangganan Tempo Digital? Lihat Disini
Manfaat berlangganan Tempo Digital? Lihat Disini