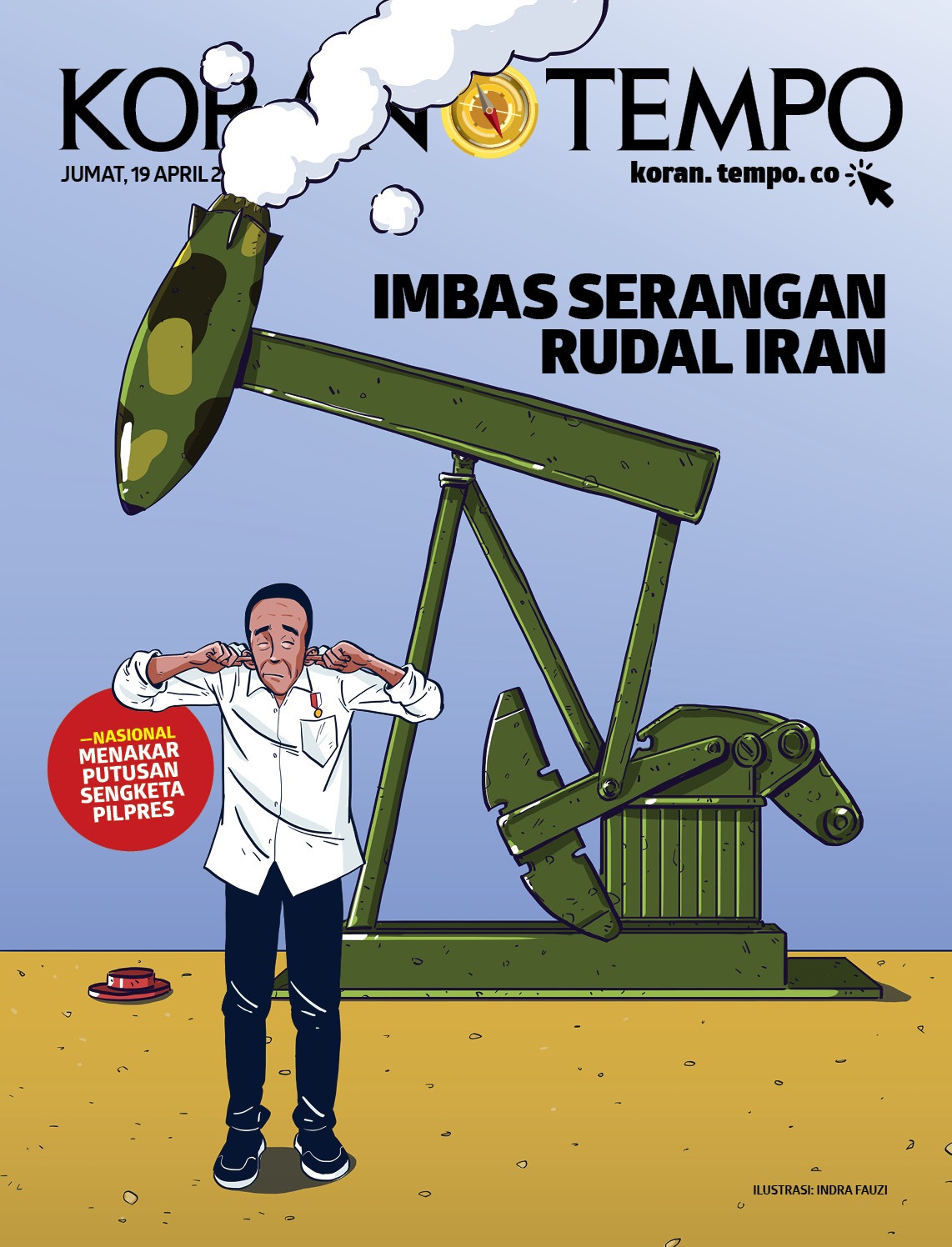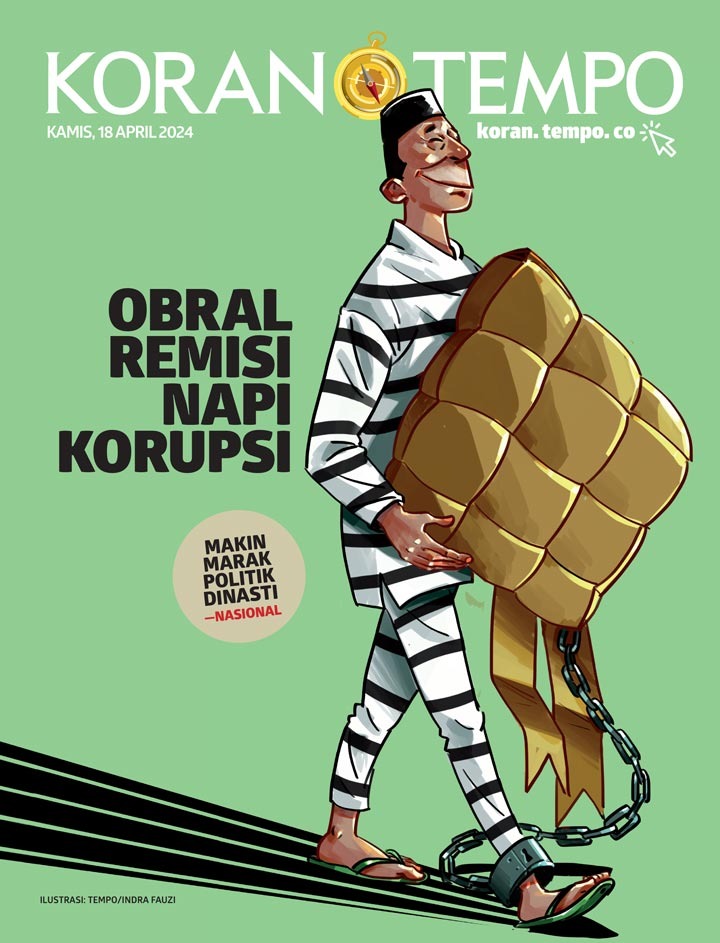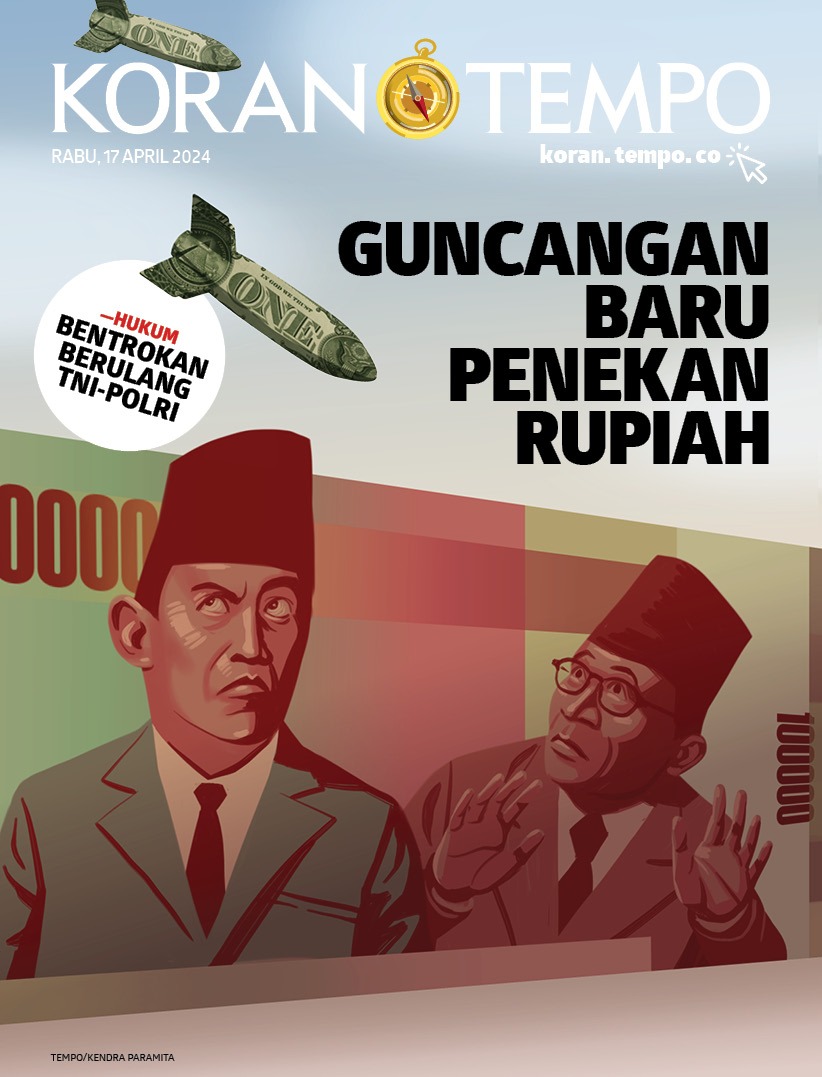Sistem Baru Pengguncang Pabrik Gula Tua
arsip tempo : 171358496513.

Khudori
Anggota Kelompok Kerja Dewan Ketahanan Pangan Pusat
Pabrik gula, yang biasanya menggiling tebu selama sekitar lima bulan, kali ini harus mengakhiri giling lebih awal menjadi hanya selama tiga bulan. Bahkan, pada 14 Agustus lalu, sudah ada pabrik yang tutup, yakni Pabrik Lestari di Nganjuk, Jawa Timur (Tempo, 2020). Saat artikel ini ditulis, boleh jadi sudah ada puluhan pabrik yang tutup giling. Mengapa hal ini terjadi?
Seperti usaha la
...
Berlangganan untuk lanjutkan membaca.
Kami mengemas berita, dengan cerita.
 Manfaat berlangganan Tempo Digital? Lihat Disini
Manfaat berlangganan Tempo Digital? Lihat Disini