Bongkar Jaringan Pengebom Makassar
Polisi perlu segera membongkar jaringan pelaku pengeboman di depan Gereja Katedral Makassar untuk mencegah kejadian serupa di kemudian hari.
arsip tempo : 171400795753.
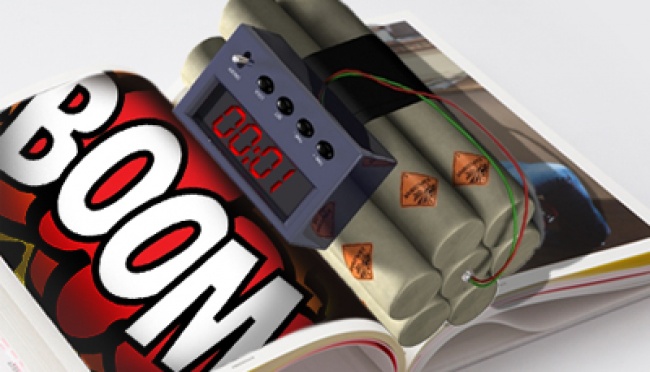
Polisi perlu segera membongkar jaringan pelaku pengeboman di depan Gereja Katedral Makassar, Sulawesi Selatan, 28 Maret lalu. Upaya itu bukan semata untuk memberi keadilan kepada para korban, tapi juga untuk mencegah kejadian serupa di kemudian hari.
Polisi mengidentifikasi pelaku bom bunuh diri itu sebagai sepasang suami-istri yang menikah enam bulan lalu. Keduanya, menurut polisi, merupakan anggota Jamaah Ansharud Daulah (JAD), organisasi yang
...
Berlangganan untuk lanjutkan membaca.
Kami mengemas berita, dengan cerita.
 Manfaat berlangganan Tempo Digital? Lihat Disini
Manfaat berlangganan Tempo Digital? Lihat Disini











